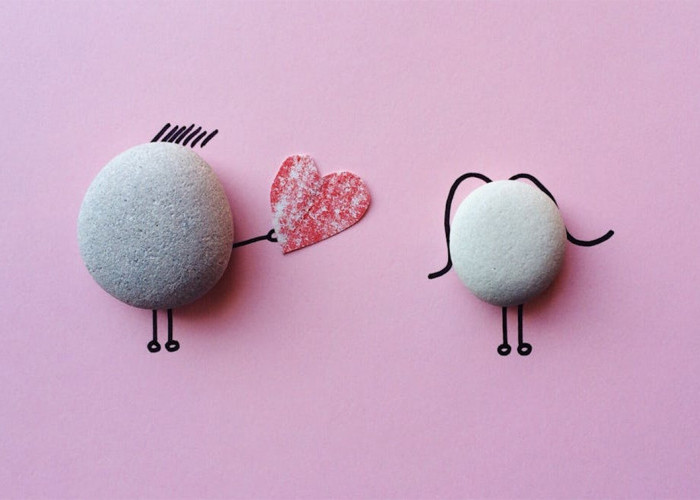Mayor Tan Tjin Kie, Hilangnya Pemakaman Megah Cina di Dukusemar Kota Cirebon

Prosesi pemakaman Mayor Tan Tjin Kie di Cirebon ditengarai sebagai salah satu yang termegah di Hindia Belanda. Bagaimana nasib makamnya saat ini? National Geographic Indonesia menurunkan sebuah tulisan tentang acara pemakaman tersebut yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala, sekaligus juga sedih. “AMPER semoea roemah ada penoeh familie dan sobat-sobatnja jang dateng mondok dari djaoeh-djaoeh [...],” Tan Gin Ho bersaksi. “[...] Di hotel-hotel banjak jang moesti tidoer di atas medja dan korsi, lantaran tida kebagian tempat.” Tan Gin Ho mengisahkan keadaan Kota Cirebon jelang pemakaman Mayor CinaTan Tjin Kie, atau yang kerap disapa warga Cirebon dengan Babah Tjin Kie. “Pendeknja kota Cheribon belon perna kadatengan orang begitoe banjak dari segala bangsa, seperti di waktoe djinazatnja Papa dikoeboer,” tulis Gin Ho. Pada masanya, inilah suasana Cirebon paling ramai sepanjang ingatan warganya. Keramaiannya, ungkap Gin Ho, jauh melebihi pengunjung perayaan Sekaten atau arak-arakan Cap Go Meh. Gin Ho merupakan putra bungsu sang mayor sendiri. Dia menulis kisah itu dalam sebuah memoar Peringetan dari Wafatnja Majoor Tan Tjin Kie. Buku kenangan itu diterbitkan oleh Druk en Cliche’s van G. Kolff & Co. di Batavia. Kendati sang ayah wafat pada Kamis, 13 Februari 1919, upacara pemakamannya baru digelar pada Rabu, 2 April 1919. Selama 1,5 bulan itu keluarga mempersiapkan upacara penghormatan terakhir nan akbar untuk sang mayor. Biaya upacaranya mencapai ƒ70.000 yang nilainya sepadan dengan emas sekitar 10 kilogram—sekitar Rp5 miliar jika diukur dengan nilai uang sekarang. Tan Tjin Kie, yang wafat dalam usia 66 tahun, merupakan seorang Tionghoa terkaya dan filantropis di Cirebon. Karirnya melecut sejak menjabat letnan tituler pada 1884, lalu bergelar Kapitein pada empat tahun berikutnya. Pemerintah Manchu menganugerahi gelar maharaja kelas II pada 1893, sementara Pemerintah Hindia Belanda memberinya penghargaan Bintang Emas untuk Pengabdian—Gouden Ster van Verdienste. Lalu, pangkat mayor titulernya disematkan pada 1913. Sang Mayor memiliki beberapa pesanggrahan bergaya hindia abad ke-19 di seantero Cirebon, seperti Roemah Pesisir, Roemah Tambak, Roemah Kalitandjoeng. Namun, Gedong Binarong, dengan pilar-pilar anggun, merupakan istana termegahnya yang bertempat di Ciledug, Kabupaten Cirebon bagian timur. Dia juga memiliki Suikerfabriek Luwunggadjah, pabrik gula yang sekaligus menjadi pabrik uangnya. Gin Ho meneruskan wasiat ayahnya untuk mendirikan masjid di kawasan pabrik gula itu “...sebab ini mesigit di nijat dibikin jang bagoes boeat bisa toeroet djadi perhiasan fabriek...” Mayor Tan Tjin Kie memang sangat dihormati. Sekitar sepuluh tahun selepas pemakaman akbar itu ahli sastra Jawa, Theodoor Gautier Thomas Pigeaud (1899 –1988), mengungkapkan bahwa sang mayor itu memiliki koleksi wayang gedok—wayang yang mementaskan cerita Panji—koleksi manuskrip, dan memiliki perhatian khusus kepada para dalang. Pigeaud pun menjuluki Tan Tjin Kie sebagai “pelindung besar kesenian Jawa”. Gin Ho melaporkan pandangan matanya soal dampak upacara pemakaman sang ayah. Sementara jalanan di Cirebon dan sekitarnya kebanjiran pengunjung, tidak demikian dengan pusat perbelanjaan. “Pasar-pasar dalem kota semoea kosong, tida ada jang djoealan,” tulisnya. “Djangan lagi pasar-pasar di kota; pasar-pasar di loear kota [...] djoega djadi kosong.” Peti jenazah diangkut keluar dari rumah duka oleh 60 orang Tionghoa berbusana dan topong serba putih. Kemudian dengan cepat zonder ada suara, peti yang berkilau itu diangkut ke atas kereta jenazah. Kereta itu ditarik oleh 240 orang Tionghoa. “Perak-peraknja peti berkilat ketjorot oleh mata hari, lantas barisan militair kasih salvo,” tulis Tan Gin Ho. Arak-arakan upacara pemakaman sang mayor ini terdiri atas sembilan kelompok yang panjangnya hampir satu kilometer. Mereka berjalan dari rumah duka hingga ke peristirahatan terakhirnya di Dukusemar, Cirebon. Sementara itu konvoi mobil pelayat, kereta dan kahar yang berjalan dibelakang kereta jenazah itu panjangnya kira-kira hingga dua pal—sekitar tiga kilometer lebih! Jelas itu adalah hari yang sibuk dan panjang untuk polisi. Sepanjang jalan menuju permakaman, setiap 20 meter tempak polisi berjaga di kanan dan kiri jalan. Dalam arak-arakan, pun satu polisi bertugas setiap 10 meter. Gin Ho mengungkapkan, setidaknya hari itu sejumlah 600 polisi mencurahkan perhatiannya untuk menjaga ketertiban upacara ini. Pemakaman akbar Sang Mayor Cina ini dihadiri oleh keluarga Residen Cirebon C.J. Feith dan Asisten Residen A.J.H. Eijken. Pemerintah Hindia Belanda juga mengirimkan dua pleton pasukan sebagai penghormatan terakhir. Kerabat keraton Cirebon, para amtenar bumiputra, Letnan Arab dan keluarga besarnya turut melayat, demikian papar Gin Ho. Sederet opsir Cina dari luar kota: Kapiten Cina Khouw Oen Hoeij dari Batavia, Letnan Cina Thung Tjoen Ho asal Bogor, Sianseng Tan Tek Haij asal Lampegan; hingga Pangeran Ario Mangkoediningrat—yang mewakili Susuhunan Pakubuwono—dan juga Auw Yang Kee yang menjabat Konsul Jenderal Tiongkok. Gin Ho menaksir ada 200.000 orang yang hadir untuk melayat. Biaya sewa kahar atau kereta yang ditarik lembu atau kuda melonjak delapan kali lipat, sementara harga sewa mobil berlipat berjingkat-jingkat hingga empat kali. Gin Ho juga mengamati di sepanjang jalan yang dilalui iring-iringan pelayat, banyak penjual meraup untung yang berlebihan. “Waroengan ada djoeal aer per kendi ƒ1,” catatnya. “Sepintjoek nasi jang harga bijasa tjoema 1 cent, di djoeal boeat 10 cent ka atas.” Tak hanya pedagang makanan atau minuman yang menjaring untung di hari pemakaman Mayor Tan Tjin Kie, tetapi juga pemilik tribun bambu yang didesain bertingkat khusus untuk menonton perhelatan akbar ini. Para penyewa kursi tribun itu tak berbatas bangsa—orang Tionghoa, Eropa, dan bumiputra, demikian ungkap Gin Ho. Kendati demikian, banyak juga orang yang tidak kebagian tempat. Mereka menyaksikan iring-iringan upacara pemakaman itu dari loteng-loteng rumah atau pepohonan di tepi jalan. “Boekan sadja toean-toean Europa tapi ada bebrapa njonja-njonja of [atau] nona-nona Eropa jang toeroet naek di poehoen-poehoen.\" Tatkala kereta jenazah lewat, suasana senyap dan takzim. Para pelayat tak berani beruara keras. Mereka yang berada di tepian jalan pun menghormatinya. Orang-orang Eropa membuka topi mereka, sementara nyonya-nyoya Tionghoa bersoja—memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan dalam tradisi Konghucu. “Maski orang ada begitoe banjak dan di antaranja ada banjak jang koerang makan dan koerang tidoer,\" tulis Gin Ho, \"tapi dari kasihannja Toehan Jang Maha Kwasa semoeannja ada slamet, tida ada kedjadian katjilakaan sewatoe apa.” Peristiwa akbar itu belum genap seabad, namun apakah kota yang pernah dibangun Tan Tjin Kie juga mengenang dan merawat tinggalannya? Sam Setyautama, seorang akuntan dan peminat budaya Tionghoa, memberi kesaksian soal kabar terakhir makam Mayor Tan Tjin Kie. Dalam buku karyanya, Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia, Sam mengisahkan pelancongannya ke Dukusemar pada awal 2004. “Mereka tahu itu daerah bekas kuburan sang mayor,” Sam menulis. “Nisannya ditemukan sudah menjadi pijakan melintas gorong-gorong.” Makam sang mayor itu berada di sekitar rumah susun dan Puskesmas Desa Dukusemar, demikian Sam bersaksi. Sayangnya makam mewah itu telah diratakan pada 1990, ungkap Sam, dan kini telah menjelma menjadi permukiman warga. “Mereka tahu itu daerah bekas kuburan sang mayor,” Sam menulis. “Nisannya ditemukan sudah menjadi pijakan melintas gorong-gorong.” Kemudian, Sam juga menambahkan, “Istana Binarong mungkin juga sudah lenyap pada 1922.” Kenangan tentang orang Tionghoa terkaya di Cirebon pada awal abad ke-20 pun tampaknya sirna sudah. Tan Tjin Kie tidak sendirian. Sebagian besar opsir Cina lain di berbagai kota juga mengalami nasib serupa. Bagaimana mungkin makam-makam itu lenyap bak ditelan Bumi? Agni Malagina, ahli sinologi dari Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia, berkomentar soal minimnya makam para opsir Cina yang selamat melintasi zaman. Menurutnya, keturunan mereka tidak perhatian lagi lantaran garis keluarga sudah putus, atau banyak keturunan mereka yang tak lagi tinggal di Indonesia—mungkin terkait soal bisnis atau politik. Kemudian, berangsur-angsur makam keluarga itu terbengkalai, seolah tak bertuan, dan tergusur untuk permukiman warga pendatang. Salah satu alasan penggusuran, mungkin pemerintah tak lagi menjumpai sertifikat kepemilikan tanah itu. Ketika zaman kemerdekaan,\" ungkap Agni Malagina, \"makam-makam yang tanahnya luas dan cuma ada dua-tiga kuburan akhirnya diduduki warga.” “Makam-makam kapitein atau mayor itu biasanya [berlokasi] di dekat rumahnya atau dimakamkan di tempat permakaman pribadi, bukan permakaman umum,” ujar Agni. Kompleks permakaman itu, imbuhnya, biasanya luas dan hanya berisi beberapa makam. “Ketika zaman kemerdekaan, makam-makam yang tanahnya luas dan cuma ada dua-tiga kuburan akhirnya diduduki warga.” Kemegahan peradaban yang berakhir mengenaskan! (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: