Refleksi Sejarah: Polemik Keraton Cirebon
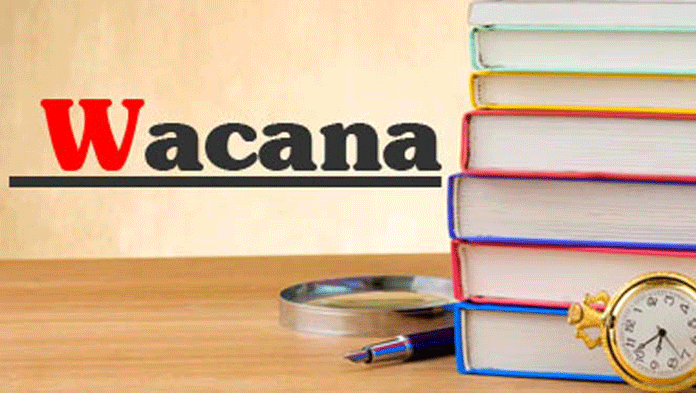
Oleh: Dr. Eva Nur Arovah, M. Hum
KEGADUHAN yang kini sedang terjadi di lingkungan Keraton Kasepuhan (disertai keterlibatan pihak-pihak lain) pada dasarnya adalah rentetan permasalahan keraton pada masa lalu yang berlanjut. Terus direproduksi hingga kini dengan pola yang mirip. Artinya, konflik yang terjadi tidaklah a-historis.
Kita bahkan bisa menelisik jejak kemunculannya sejak beberapa ratusan tahun yang lalu sampai kini. Yang menjadi pembeda peristiwa konfliknya hanya waktu dan pelaku, sementara inti dari persoalan nyatanya tidak pernah jauh dari persoalan politik yang berhubungan dengan suksesi kepemimpinan dan kepentingan ekonomi, persoalan tanah di antaranya.
Suksesi Kepemimpinan dan Persoalan Tanah
Kepemimpinan Kerajaan Islam Cirebon tidak bisa lepas dari sosok Sunan Gunung Jati. Sebagai pemegang otoritas politik dan keagamaan, Sunan Gunung Jati nyatanya ditempatkan oleh pemeluk Islam pada posisi yang sangat terhormat. Kepemimpinannya secara umum dipandang kharismatik sekaligus menyebar hingga ke kelompok beragam tanpa menimbulkan konflik berarti.
Sampai dengan paruh kedua abad 17, melalui pemimpin Kerajaan Islam berikutnya, yakni Penembahan Ratu (Cicit Sunan Gunung Jati) kedaulatan kerajaan dan wibawa keagamaan Sunan Gunung Jati masih berdiri kokoh.
Tanda-tanda perubahan radikal terjadi sejak meninggalnya Panembahan Girilaya di Mataram. Sekaligus menandai berakhirnya kerajaan Islam Cirebon yang nantinya diikuti berbagai perubahan politik secara signifikan, utamanya persoalan perpecahan kerajaan.
Memasuki akhir 1677, bertempat di Banten, ketiga putra Panembahan Girilaya (Pangeran Martawijaya, Pangeran Kertawijaya, dan Pangeran Wangsakerta) dilantik oleh Sultan Ageng Tirtayasa sebagai tiga penguasa Cirebon: (1) Pangeran Martawijaya sebagai Sultan Kasepuhan dengan gelar Sultan Muhamad Samsudin. (2) Pangeran Kartawijaya sebagai sultan Kanoman dengan gelar Sultan Muhamad Badridin, dan (3) Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon (Dagh Register 1678: 58).
Hal ini berarti pada abad ke-17 Kerajaan Islam Cirebon pecah menjadi dua keraton dan satu peguron yang saling berdampingan yang berakibat pada, meski satu “Cirebon”, tanpa terasa para pangeran Cirebon pada waktu itu membentuk satu kesatuan yang lemah dan berdampak pada perubahan kewajiban, kekuasaan, hak, fungsi, serta mengancam stabilitas keseimbangan kekuasaan di Cirebon. Lokus yang paling mendesak dari persoalan ini adalah munculnya pemimpin-pemimin baru disertai dengan ketegangan yang tidak pernah sepenuhnya tercairkan. Yakni persoalan suksesi kekuasaan, perebutan pengaruh dan wibawa, serta hak-hak masing-masing pangeran mencakup wilayah atau tanah.
Baca juga:
- Dewan Famili Kesultanan Cirebon Siap Mediasi Polemik Takhta Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan
- Penobatan Sultan Sepuh XV Undang Presiden Hingga Raja Nusantara
Lebih dari itu, pertarungan yang terus menerus untuk memperebutkan kekuasaan sampai pada tahap melahirkan keraton-keraton baru sebagaimana yang terjadi pada Keraton Kasepuhan maupun Keraton Kanoman. Catatan tentang konflik Keraton Kasepuhan menyebutkan dimulai dengan peristiwa meninggalnya Sultan Sepuh I yang disusul dengan pecahnya Kasepuhan menjadi Kasepuhan dan Kacerbonan yang berdiri sejak 1697 sampai dengan 1723 dengan Pangeran Aria Cerbon sebagai pemimpinnya.
Konflik besar dan keruwetan di Kasepuhan lainnya terjadi pada masa Sultan Sepuh Shafiuddin Matangaji (1773-1778). Sementara di Keraton Kanoman, perbedaan orientasi para anak sultan menyebabkan lahirnya Peguron Kaprabonan pada 1679. Berikutnya, antara akhir abad ke-18 hingga paroh pertama abad ke-19 terjadi kecamuk besar di Kanoman hingga melahirkan Keraton Kacerbonan pada 1808. Persoalan suksesi sultan Kanoman bahkan kembali memanas ketika memasuki tahun 2000-an.
Untuk beberapa waktu lamanya, konflik penguasa tradisional di atas masih dibarengi dengan kekacauan ekonomi, wabah penyakit, serta proses perubahan sosial-budaya yang berjalan terus menerus dalam wujud permasalahannya hingga memasuki abad ke-19. Sejajar dengan “kemunduran” yang terjadi pada keraton-keraton Cirebon di atas, VOC yang sudah hadir di Cirebon segera memantapkan intervesinya dan mengambil keuntungan dari intrik-intrik dalam pertentangan di antara para pangeran dan bangsawan. Wakil-wakil VOC dengan semangat menawarkan diri untuk menjadi “pendukung” sekaligus “penengah” pada beberapa perjanjian antarsultan.
Nyatanya, yang terjadi kemudian adalah segelintir orang sebagai wakil VOC yang memperdaya para pangeran guna menciptakan dominasi dan tercapainya kepentingan mereka. Campur tangan dan aturan-aturan VOC yang terkadang terlihat bias dalam persoalan legitimasi terhadap suksesi pada keraton Cirebon menyebabkan timbulnya situasi yang rumit.
Sampai pada masa Daendels status para sultan menjadi pegawai dan masih diperkenankan memakai gelar sultan tetapi bersifat gelar titular (sementara). Dan pada masa Raffles, para sultan Cirebon dipensiunkan, dianeksasi hingga kasultanan Cirebon dihapus dan mereka hanya dianggap sebagai “pemangku adat” atau informal leader Cirebon (Siddique, 1977: 45).
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:










