Membentuk Jiwa Bangsa Melalui Sastra
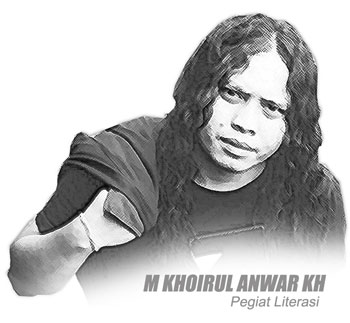
Art is a lie that reveals the truth,
Charles Dickens MEMBACA geliat literasi yang mulai tumbuh belakangan ini, imajinasi penulis seperti diajak bertamasya ke labirin masa lalu. Labirin yang mengetengahkan betapa daerah pesisir ini mempunyai tradisi literasi yang amat panjang dan dahsyat. Labirin yang membuat penulis memahami fakta sejarah bahwa Cirebon, tempat penulis lahir dan tumbuh, tidak melulu dibangun dari sisa-sisa adab pelabuhan dan perdagangan, tapi juga dari peradaban literasi yang sanggup menenun sejarah hingga bisa kita baca dan khidmati sampai detik ini. Di sini. Penulis mengamini Untung Rahardjo yang telah coba meraba periodisasi dan kategorisasi tapak jejak susastra Cirebon di dalam bukunya: Kesusastraan Cirebon (Dalam Periodeisasi Kuna, Tengahan, Baru dan Modern). Untung memulainya dari masa kesusastraan Cirebon di era klasik (Kuna). Di era inilah kesusastraan Cirebon mengalami dentuman yang gigantik. Ini ditandai dengan massifnya karya-karya sastra yang lahir untuk menanggapi fenomena sosio-politik yang berkelebat saat itu. Periode ini dimulai dari alaf 1445 M hingga Pangeran Wangsakerta menggagas Gotrasawala pada titimangsa 1677 (Rahardjo, 2004:17). Karya-karya masterpiece lahir di era ini. Dari mulai Purwaka Samasta Bhuwana karya Pangeran Losari (17 jilid), Pustaka dan Rontal zaman Panembahan Ratu (91 jilid), naskah Ramayana (7 jilid), Pustaka Agama Islam karya Pangeran Manis dkk (300 jilid), Sarwacarita yang muncul era panembahan Girilaya (75 jilid). Tak hanya itu, seperti yang sudah diketengahkan Wangsakerta dalam Pustaka Rajya-rajya I Bhumi Nusantara, Parwa V, Sarga V, bahwa di era tersebut terdapat beberapa karya magnum opus seperti: Pustaka Rajya-rajya I Bhumi Nusantara (25 jilid), Pustaka Pararatwan (10 jilid), Pustaka Negara Kretabhumi (12 jilid), dan puluhan bahkan ratusan naskah lainnya. Bahkan Sunan Gunung Jati sendiri menulis karya berupa Silsilah Raja-Raja Sunda. Sedangkan produk sastra yang lazim digunakan pada saat itu di antaranya: Kakawen (sajak campuran), Kidung (tembang), Gugon Tuwon (nasihat kehidupan), dan Jawokan (mantra/doa). Kakawen banyak dijumpai di naskah-naskah Wangsakerta. Beberapa contoh kidung adalah Kidung Rajah Kala Cakra, Kidung Sarab Sawan, dan Kidung Tulak Tanggul. Gugon Tuwon sendiri lazim digunakan sesepuh-sesepuh Cirebon, seperti Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana, dan Ki Kuwu Sangkan. Setelah itu era sastra Cirebon masuk ke fase Tengahan. Ini berlangsung sejak 1700 M sampai 1800 M. Di fase ini, karya-karya yang lahir di antaranya: Carita Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Carbon (1720 M), Pepakem Jaksa Pepitu (1765 M), Pustaka Pakungwati Carbon karya antologi Ki Wangsa Manggala dkk (1779 M), Babad Ratu Carbon Girang karya Ki Somad Manggala 1790 M, Wewacan Cerbon karya Ki Demang Pamayahan (1805 M), Catur Kanda karya Pangeran Arya Suradiningrat (1848 M), Babad Galuh karya Kiai Surengrana (1876 M). Tipologi sastranya meliputi Macapat, Pralampita, Sandisastra, Sasmita, dan Panyandra. Periode Baru jatuh pada dekade 1800 akhir sampai pertengahan 1900 M. Produk literasi yang lahir di era ini bisa kita eja mulai: Sejarah Cerbon karya Harya Dendaningrat (1886 M) dan Serat Suluk Bangun Umah karya Raden Duliyas Bratakusuma (1956 M). Ekspresi susastranya sangat variatif. Dari Wangsalan, Parikan, Paribasa/Pribasa, Sanepa, Ukara Sesumbar, Basa Prenesan, hingga Basa Rinengga (Rineka). Periode Modern diperkirakan dimulai 1950 hingga kini. Di periode ini sastra Cirebon sudah mulai terpuruk dan kurang bergairah. Ini ditandai dengan lahirnya bahasa ungkap yang hanya berupa geguritan. Baik yang bernafaskan macapat maupun yang tak beraturan seperti halnya puisi bebas. Sejujurnya, tak banyak karya yang bisa ditemukan di fase-fase ini selain karya-karya sambilan yang bisa kita temukan secara fluktuatif di beberapa media masa lokal atau antologi puisi komunitas yang masih menggenggam sastra Cirebon dalam dadanya. Seperti ucap Syubanuddin Alwy: saat ini sastra Cirebon berada dalam lingkungan yang terbatas. Ia hanya ditulis oleh segelintir orang. Mayoritas ditulis dalam genre karya sastra yang ditulis dalam skala imajinasi para pemula (Apa Kabar, Bahasa dan Sastra Cirebon?, hlm: 07). GEGAR LITERASI BUDAYA Di musim pilpres dua tahun lalu, jagat media sosial kita kembali riuh-bergemuruh. Bukan lantaran selebrasi sensasional yang kerap ditebarkan para artis, juga bukan sebab ancaman radikalisme yang kini tengah kembali meradang. Melainkan karena pernyataan salah satu petinggi partai di republik ini yang berseloroh: pengumpulan data kecurangan pilpres ke Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan seperti Roro Jonggrang membuat Tangkuban Perahu (03/08/14). Terlepas dari ramainya kontroversi yang mengemuka, ada hal substansial yang mustinya diperbincangkan lebih lanjut. Kita bisa memulainya dari pertanyaan sebagai berikut: bagaimana mungkin manusia Indonesia yang menduduki jabatan strategis dalam sebuah partai mengalami “buta literasi-budaya” sedemikian? Mengapa mayoritas orang dewasa abad ini seakan mulai mengalami penyakit psikologis berupa tuna literasi budaya? Tidak hanya mereka yang duduk di pucuk pimpinan semata, tapi nyaris seluruh lini masyarakat menganggap literasi budaya (dahulu) tak ubahnya klangenan atau bahkan hiburan semata. Ini disebabkan, di antaranya, karena sedari dini kita tak dikenalkan dengan khazanah (kesusastraan) lokal dengan sungguh-sungguh. Muatan-muatan lokal yang lazim ditemui di sekolah hanya dianggap sebatas ekstra-kurikuler yang tak merasuk sebagai prioritas. Ini ditambah dengan dikotomi yang lahir di kalangan masyarakat terdidik bahwa eksakta jauh lebih menjanjikan ketimbang humaniora. Padahal, sastra menghaluskan rasa dan eksakta menajamkan isi kepala. Keduanya seperti dua sisi mata koin yang tak dapat dipisahkan. Bukankah, manusia tak melulu produk akal-pikir seperti yang digaungkan oleh aufklarung maupun renaisans? Tapi juga entitas yang memiliki rasa dan jiwa. RENAISANS SASTRA (DAERAH) Melihat kondisi susastra daerah yang sudah sedemikian menggiriskan, tentu perlu beberapa langkah jitu agar sastra tak terperosok dalam jurang curam sejarah. Karena itu, tawaran di sini mungkin layak diperhitungkan demi kebangkitan kembali sastra daerah, Cirebon khususnya, menuju puncak kejayaannya seperti era Wangsakerta dulu. Pertama, mentradisikan penggunaan piranti sastra daerah dalam hidup keseharian, semisal guritan atau lainnya. Kedua, mendidik anak sejak dini untuk mengenal sastra tidak saja dari bangku sekolah, tapi juga lingkungan sosio-kultur yang melingkupinya. Ketiga, sedari kini pendidik musti coba memulai menggunakan pitutur sastra daerah dalam mentransfer pengetahuan di bangku-bangku lembaga pendidikan. Keempat, mengemas pelbagai khazanah sastra daerah yang kaya itu melalui seni visual (film) maupun media informasi lainnya (Suyanto, 10/15/15). Kelima, kerja sama media massa dalam (kembali) mempopulerkan susastra daerah dalam bentuknya yang segar dan baru. Terakhir, tentu saja, itikad baik pemerintah baik pusat maupun daerah demi kemajuan sastra baik berupa legislasi maupun (terlebih) apresiasi. Saatnya berhenti mengutuk kegelapan. Apa yang dicanangkan para pendahulu adalah langkah awal yang perlu kita urai lebih lanjut dan mendalam. Mari jadikan gagasan renaisans sastra (daerah) sebagai gagasan semesta. Kita patut iri pada AA Navis yang mengungkap budaya Melayu melalui Robohnya Surau Kami, Linus Suryadi AG yang mengungkap tradisi Jawa melalui Pengakuan Pariyem, Ahmad Tohari yang menyingkap nilai budaya Jawa Banyumas melalui trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, dan semua sastrawan yang mengusung lokalitas budaya dalam setiap denyut karyanya. Penulis ingin menutup esai ini dengan mengutip Kakawen dari Pangeran Wangsakerta. Kakawen yang musti kita renungkan dengan takzim dan seksama demi keberlangsungan susastra di masa depan: Awignam astu/ swasti/ telas sinusun mwang sinerat sayampratar tan henti/ dening pirang sang manurat sinerat ri Sakakala/ Nawa gapura marga raja/ eka suklapaksa/ Srewana masa/ Nihan ta/ mangdadiyakna dirga yusawastisanira sang manurat sang amaca/ sang anggogoh mwang sang angupakareka pustaka/ sang tasmat yadiyan hana kaluputan athawa kasasar ing serat sastrei/ waraksmakna ta. “Mudah-mudahan tiada aral melintang. Semoga selamat. Telah disusun dan ditulis siang malam, tiada henti-hentinya oleh sejumlah penulis. Ditulis pada tahun saka: Nawa Gapura Marga Raja (1599 S./1677 M.), tanggal 1 paro terang bulan Srawana (02 Juli). Demikianlah semoga panjang-panjang usianya, bagi yang menulis, yang membaca, yang menyimpan, dan yang memelihara naskah ini. Maka apabila kesalahan atau kekeliruan tulisan sastra ini, maafkanlah” (cuplikan naskah Pangeran Wangsakerta, 1677 M., Rajya-rajya 1 Bhumi Nusantara, Sargah I, Parwa I, bait 224). Saat ini kita butuh manusia-manusia yang memiliki kapasitas keuletan sekaliber Pangeran Wangsakerta. Manusia yang setiap inci waktunya mendedikasikan diri untuk membaca, menulis, mendokumentasi, dan mereproduksi karya susastra sesuai dengan konteks zaman yang melingkupinya. Manusia-manusia yang menganggap sastra tak semata sebagai korpus mati yang musti dielus-elus di laci museum sejarah. Tapi senantiasa diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelbagai medium dan cara. Percayalah, hingga detik ini susastra merupakan piranti paling ampuh dalam membentuk gerabah karakter jiwa sebuah bangsa. Penulis bermimpi, jika melalui Andrea Hirata dunia mampu mengenal Belitong sebagai negeri Laskar Pelangi, maka sudah saatnya masyarakat global mengenal titik koordinat Cirebon tidak semata hanya dari Tari Topeng, Sintren maupun Keraton. Tapi juga dari wisata literasi yang melimpah-ruah wujudnya. Begitu juga dengan susastra daerah-daerah lainnya di sekujur Indonesia yang menunggu untuk kembali dielaborasi makna dan bentuknya. Bagaimana menurut Anda? *) Penulis adalah Penggiat Literasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:










