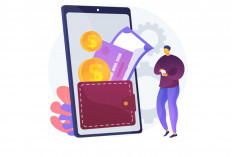Cirebon, Bahasa Ibu, dan Kita yang Anu…

BAHASA adalah sistem tanda (signifier/signified)—demikian kaum post-strukturalis, bukan saja mewakili benda-benda, tapi juga struktur sosial, tertib berpikir, ideologi, bahkan sesuatu yang paling abstrak: habitus. Karenanya setiap ide, simbol, metafor, gagasan, konsep, etika, atau estetika yang mengabstraksikan satu kesadaran dan pandangan tertentu, terwakili susunan kata yang senantiasa hendak melengkapi komunikasi simbol-simbol. Bahasa memang serupa gema. Di tahun 1989, Ecole des Hautes Etudes en Sciences, Paris, menerbitkan tiga jilid buku Nusa Jawa: Silang Budaya, hasil tiga puluh tahun penelitian Prof. DR Dennys Lombard. Di sana, Pulau Jawa terbagi dalam tiga lapis sosial-budaya besar: Pasundan, Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta) dan Pesisir. Untuk yang terakhir, sejarawan dan antropolog asal Perancis itu menunjuk pada lajur pantai utara dimana identitas Jawa dan Sunda melemah, bahkan menghilang, dan tergantikan oleh sebuah silang budaya yang jauh lebih kosmopolit dengan dimensi universalnya. Seperti sudah terungkap, abad 15-16 M adalah masa-masa penting bagi sejarah perkembangan kawasan pesisir. Surabaya memang sudah menjadi pelabuhan internasional pada abad ke-14, namun baru seabad berikutnya kemajuan-kemajuan diraih kota-kota pesisir: ketika komunitas Cina awal mulai menetap, Islamisasi berlangsung, dan Kesultanan Demak didirikan. Menariknya, setiap kemajuan yang dicapai masing-masing pelabuhan (ekonomi maritim), selalu berbanding lurus dengan kejatuhan kompetitornya. Di sebelah timur, kita bisa melihat bagaimana Surabaya menjadi besar di atas kerugian yang dialami Tuban dan Gresik (abad 16). Di bagian tengah, setelah lonjakan Demak di abad ke-16, Mataram kembali memperkuat pengaruhnya di kawasan pesisir. Perdagangan maritim di Jepara pun dikuasainya. Pada saat itulah, Semarang mulai bangkit, lalu benar-benar berhasil mengalahkan saingannya (abad 18). Sementara di Barat, Kesultanan Banten meraksasa (abad 16) setelah pelabuhan pra-Islam Kelapa (Jayakarta/Batavia/Jakarta) perlahan mengalami kemunduran. Namun Batavia yang dibangun pada abad 17 di atas situs Kelapa, berhasil kembali mengungguli Banten dan bukan saja tumbuh menjadi kota terpenting di Jawa, tapi juga di seluruh kepulauan nusantara. Yang tak kalah menarik—barangkali karena takdir geografis dan geopolitik, Cirebon malah berhasil mengisolasi diri dari perseteruan dan gesekan kepentingan antara penguasa Mataram dan VOC. Alhasil, sebagai sebuah kota persilangan berukuran sedang, Cirebon mampu terus-menerus bertahan sejak abad 16 hingga sekarang. Cirebon pun menjadi yang paling kosmopolit dibanding daerah lain di seluruh kawasan pesisir. Serpihan budaya Jawa, Sunda, Cina, India, Arab, Baghdad, bahkan Eropa, masih benar terasa. Istilah Caruban sendiri menjadi indikator tepat bagi identitas yang terlahir dari pergumulan banyak anasir budaya. Bahasa Cirebon pun terkayakan. Sampai saat kita diherankan oleh kenyataan bahwa di kota yang paling intens berakulturasi itu, tak didapati padanan kata “kita” dan “mereka” dalam bahasa lokalnya. Dalam bahasa Indonesia, kata “saya” (asal kata sahaya) menjadi kata ganti orang pertama yang menunjukkan hirarki sosial dalam suatu masyarakat tertentu. Kita tahu, “sahaya” menjadi yang inferior di hadapan yang superior, subordinat pada yang ordinat, klien terhadap patron, hingga akhirnya menjelaskan pola hubungan tuan-hamba. Kata “ambo” berasal dari kata “hamba” yang selalu diinjak-injak tuannya itu. Begitu pula “abdi” dan “budak” dalam bahasa sunda, “kula” (kawula) dan “isun” (ingsun) dalam bahasa Jawa/Cirebon. Simbol-simbol tak otonom tersebut memiliki kolerasi positif dengan pengalaman sosial bangsa-bangsa nusantara yang memang terjajah di hampir semua babak sejarah. Pertanyaannya: jika benar bahasa adalah bayangan ide dan imajinasi, fenomena dan kesadaran yang dipantulkan, lalu di manakah kata “kita” dan “mereka” dalam masyarakat yang pluralnya minta ampun itu? Ada tiga kemungkinan. Pertama, Cirebon tidak cukup peka menjadi penanda atas detail fenomena. Ini mudah dilewat, mengingat ada banyak sekali kata tak bersayap dalam bahasa yang oleh Ayatrohaedi disebut sebagai bahasa daerah terbesar ketiga di Indonesia itu. Sebut saja kata “lawas” dan “sue”. Bahasa Indonesia hanya menyediakan kata “lama” untuk menggantinya. Padahal sekalipun sama-sama terperangkap titimangsa, kedua kata tersebut begitu beda. Sue adalah keterangan waktu yang bernuansa kerja, sedangkan lawas menjadi keterangan waktu dalam adjektiva. Masalah ini dialami juga oleh antonim kedua kata tersebut: “anyar” (new) dan “nembe” (just now). Kecermatan bahasa Cirebon bisa dilihat dari kalimat, klambine anyar, nembe tuku (bajunya [baru], [baru] beli). Dalam bahasa Cirebon, kata “jalan” saja memiliki kadar dan tingkatan. Jika pelan, disebut “melaku”. Sedikit lebih cepat, disebut “kentig”. Lebih cepat lagi, disebut “kentig saman”. Lebih cepat dari kentig saman, disebut “kipit”. Lebih cepat dari kipit, disebut “ingkrig”. Di hadapan semua, bahasa Indonesia hanya bisa plonga-plongo. Kedua, heterogenitas budaya tidak baur dalam situasi pri dan nonpri. Garis demarkasi tak ditarik di antaranya. Sangat mungkin sikap permisif menjadi atmosfir bersama ketika itu. Sebab kata “kita” dan “mereka”, niscaya terlahir dari satu ketegangan identitas yang masing-masing hendak mempertahankan jarak dan kebedaannya. Namun di kota yang memiliki tiga keraton ini, dengan sejenak mengenyampingkan berbagai akulturasi yang berlangsung, fragmentasi identitas ternyata terjadi di mana-mana. Kita bisa melihatnya dari toponimi yang menunjukkan adanya kolonisasi komunitas sosial seperti Pecinan (komunitas pedagang Cina), Panjunan (untuk tukang poci dari arab), Pagongan (pengrajin tembaga), Pekiringan (pembuat tekstil dan barang anyaman), dan Pekalangan (penduduk hutan yang dipindahkan ke kota sejak abad 17 untuk menjadi tukang kayu), yang semua kini masih bertahan. Dengan demikian, kemungkinan terakhir menjadi yang paling logis: ada sejumlah kosakata yang menipis, terpinggirkan, dan akhirnya sirna ilang kertaning bumi. Tentu saja ini hanya qarinah, sesuatu yang ditarik dari jejalin indikasi. Kita tahu, seiring kebijakan pemerintah daerah yang kerap asal njeplak, penutur bahasa Cirebon ternyata terus berkurang. Kosakata-kosakata pun telah banyak berguguran. Misalnya kata “pecira” yang kini terganti oleh ruang tamu, kata “blagbag” yang menjadi papan tulis, begitu juga dengan kata “seroal” dan “sosi”. Ke mana juga perginya kenceng dan keplek? Tempolong, blegedeg, pangkeng, dan kotrek? Barangkali bukan hanya bahasa Cirebon. Empat ratus sekian bahasa daerah yang tersebar di ghetto-ghetto nusantara, diam-diam tengah menghadapi kepungan milenial yang begitu verbal dan “kanibal”. Bahasa yang bergentayangan di berbagai media seperti bersiap menasakh tiap kata yang sebenarnya sudah puput, balig, hingga akhirnya mandiri dalam bahasa. Di sisi lain, tidak semua bahasa daerah memiliki cukup genius untuk bisa bersikap terbuka seraya tetap menjaga kemampuan eklektiksismenya. Bahasa Indonesia bahkan tidak bisa menjadi pengecualian. Pada lingua franca (Kun-lun; melayu; bahasa Indonesia), penyerapan banyak kosakata dari bahasa Sansekerta, Arab, Persia, Hindustan, Tamil, Talugu, Siam, Cina, Portugis, Belanda, dan Inggris, diikuti arah sebaliknya: lingua franca memberi pengaruh juga pada bahasa Tagalog, Cam, Siam, Arab, Afrika, Belanda, Portugis, Inggris, dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Namun kini kita menyaksikan berbondong-bondong kata diimpor dari Eropa, Arab, dan Amerika, seakan bahasa Indonesia tak mampu menjangkaunya. Untuk kata atau idiom tertentu, banyak penulis kerap mencantumkan padanan bahasa Inggris dalam tanda kurung. Kadang membantu, meski lebih sering terlihat genit dan norak. Pada kasus, “pembagian kerja (division of labour)”, “manajemen konflik (managed conflict)”, “faktor tak terkontrol (uncontrolled factor)”, “negara (state)” atau “kemajuan (progress)”, semua hanya mengesankan seorang penulis yang, sambil berharap-harap cemas, pengin dianggap pintar. Hingga bagi saya, persoalan pokok seluruh bahasa yang tersebar di seantero nusantara adalah kecintaan dan kebanggaan yang terdegradasi justru oleh ahli warisnya sendiri. Di Cirebon Kota, orang-orang gampang sarkastis tiap kali mendengar segala yang medok. Padahal penutur lahir di Cirebon, dibesarkan di Cirebon, lawan bicara dari Cirebon, perbincangan terjadi di tanah Cirebon, dan pendengar sendiri warga Cirebon. Sementara pada saat yang sama, kita selalu mafhum pada Desi Ratnasari dengan bahasa Indonesianya yang kesunda-sundaan, Yeyen yang kejawa-jawaan, Butet yang kebatak-batakan, Deswita Maharani yang kebetawi-betawian, dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali soalnya karena Cirebon bukan lagi “Cirebon”. Apa yang oleh Quaritch Wales sebut sebagai local genius, di sini diperlakukan dengan tidak jenius. Ada semacam kecenderungan yang hendak menegasikan niai-nilai lokal yang tipikalis, seraya mengafirmasi karnaval panjang yang terus menerobos pusaran arus kebudayaan daerah. Sampai di sini, apa yang disebut sebagai Cerbon, basa Cerbon, wong Cerbon hanyalah kekaburan-kekaburan identitas yang dirayakan setiap saat. Orang mengira dirinya muasal kata. Padahal hanya serupa bahasa. Serupa gema. Bahkan dalam daya releksi diri, dalam tiap identifikasi genealogi yang menautkan dependensi-dependensi, kita sesekali merasa seperti—meminjam bait puisi Amir Hamzah, gema tiada berupa. (*) *Bukan Budayawan, tinggal di Rumah Kertas
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: