Arsitektur Mudik
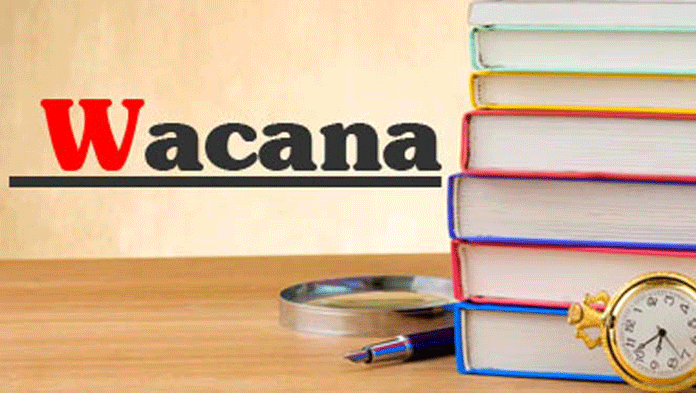
SAYA bayangkan (entah saya membayangkan), bahwa di Jakarta, ia sebagai kuli panggil, mungkin penjaga sekolah SD, mungkin loper koran, atau mungkin pegawai pabrik; tinggal di sebuah bilik yang siapa tahu kumuh atau rumah sederhana dengan dinding geripis. Jelasnya, ia, satu dari jutaan manusia yang, sebelum sampai di sini, bersiap mudik ke kampung halaman. Ia, satu dari jutaan manusia yang melintasi jalan“berdarah” Anyer-Panarukan. Bersama pula tol-tol yang dibuat skema satu arah, yang dirayapi jutaan mobil. Bus-bus antar kota yang sesak. Gerbong-gerbong kereta yang pengap. Saya lihat Kang Dulkimin merasa lega, lalu melepas helm non-SNI miliknya dari kepalanya yang berkeringat. Motor butut Astrea 700 itu, distandarkannya dekat pohon waru, di tepi galangan. Seraya mengendong tas hitam yang pias, ia berjalan gontai; wajahnya lusuh tapi mengandung optimisme. Kompleks pekuburan tanpa pagar atau gapura, hanya dikelilingi parit-parit sekaligus dirimbuni pohon-pohon mangga dan pisang, dan berada di tengah hamparan sawah itu, menyambut Kang Dulkimin. “Saya datang.” Mungkin begitu yang Kang Dulkimin ucapkan ketika memasuki pemakaman. Seperti para pelancong lain, ia, mungkin juga berujar, “Selamat tinggal Jakarta.” Mereka sadar bahwa maksudnya: tak benar-benar pergi. Meskitak benar-benar pergi, bagi Jakarta, amatlah punya arti. Bila musim mudik tiba, bukan muskil, jika orang Betawi bilang: beberape hari aje, nih Jakarte kagak nyeri lagi pinggangnye. Jakarta akan melepaskan sepatu dan ikat pingganya, beban-bebannya. Ia akan menyandar lemah di pokok pohon rambutan, jambu air, mangga, kelapa, atau durian. Tapi masihkah ada pohon-pohon yang katanya khas kampung (Betawi) itu? Ah, Jakarta bila mudik tiba: akan lengang selengang subuh hari. Tapi biasanya, saat subuh pun Jakarta masih semarak. Ia memang tak pernah tidur. Sebuah contoh kota insomnia. Atau lebih tepat: kota yang lupa cara tidur. Semenjak pupur modernisasi memoles wajah Jakarta, semenjak itulah Jakarta lupa bagaimana mendengkur. Jalan-jalan baru digelar. “Simbol-simbol kota” seperti: mal, perumahan, pabrik-pabrik, bank-bank, gedung bertingkat, infrastruktur transportasi, museum, hotel, tempat hiburan, perkantoran, rumah sakit, bangunan pendidikan, dan lain-lain, menjelma pakaian baru Jakarta, dan menjadikan kalkulasi ekonomi sebagai alam pikirnya. Jakarta pun menjadi magnet bagi orang-orang dari pelbagai daerah, dari kultur berbeda dan dengan motif yang tak semua sama. Urbanisasi membuat kota kian padat, dan ruang hidup terus dibutuhkan. Situasi ini bak gayung bersambut dengan era globalisasi, di mana privatisasi dan libelarisasi begitu kencang, ekspansi lahan serta spekulasi tanah semakin tinggi; tekanan terhadap ruang-ruang kota makin berat saja. Sehingga apa yang kita temukan kemudian adalah munculnya logika baru: pendudukan dan penggusuran. Gambar dan bayang konflik, dongkak-mendongkak di tubuh Jakarta. Dari logika semacam itulah Jakarta tak bisa dalam keadaan beku. Ia merupakan medan dari proyek ke proyek, dari booming ke booming. Jakarta selalu bergerak. Berderak. Juga mengepulkan polusi. Tetapi dalam keadaan yang tak pernah diam inilah, Kang Dulkimin dan para pelancong lain, hidup dan mengais rezeki. Dalam keadaan ombak yang senantiasa bergejolak, ketahanan seseorang teruji. Mereka dituntun untuk selalu kreatif, sebab kosmologi Jakarta akan selalu berubah dari saat ke saat. Kepada perubahaan yang bagai sebuah keniscayaan itulah seseorang dididik untuk terus beradaptasi. Mestilah licin dan tahan banting di tengah ketidakpastian. Tentu saja Jakarta bukan kampung mereka. Kosmologi di kampung mereka itu, tetap. Di kampung---sebagaimana umumnya wilayah agraris---, mereka mengalami siklus waktu yang siklik; matahari terbit di timur dan terbenam di barat, ada musim hujan dan ada musim kemarau---para petani paham apa yang dilakukan terhadap sawahnya ketika situasi-situasi ini. Ketetapan dan keteraturan, berlangsung selama berabad-abad hingga kemudian mengkristal (lantaran sublimasi yang intens) jadi ritual bernuansa religius, misal: mapag sri. Pula, kampung memilih berhati-hati terhadap perubahan. Barangkali lamban menjadikan mereka khusyuk. Segala ucapan mereka takar di kepala bagian belakang, mungkin di dalam blangkon atau sanggul. Barangkali KangDulkimin dan juga para pelancong lain di Jakarta, adalah orang-orang perbatasan itu: “yang urban” dan “yang rural”. Tetapi ada yang bilang, mereka sepenuhnya orang urban. Bukan rural. Sebab waktu yang dihabiskan mereka jauh lebih banyak di dunia urban. Kang Dulkimin dan para pelancong lainnya hanya menghabiskan secuil waktu di dunia rural, sehingga kemudian cukup menjadikan “yang rural” terkikis. Kang Dulkimin dan para pelancong itu, tak lebih dari masyarakat urban yang senantiasa gelisah, menghendaki tantangan dalam kegugupan. Di hadapan muatan psikologis ini, mudik, jadi sekadar upaya menjawab tantangan jalan raya. Sementara kampung halaman, “yang rural”, hanya pemanis yang lekas lapuk. Itu berarti, perjalananlah yang mereka buru, yang Kang Dulkimin cari, bukan opor ayam atau ketupat. Mungkinkah senaif itu? Mungkin saja, sebab kebergerakan, ketidakpastian, dan ketertekanan kosmologi kota macam Jakarta, telah merekonstruksi Kang Dulkimin dan para pemudik lain untuk menikmati sesuatu yang tak stagnan: perjalanan. Seorang lain mengatakan, kepemilikan waktu “yang urban”, berbeda dengan konsep kepemilikan waktu “yang rural”. Masyarakat urban tak memiliki hak “menggenggam” waktu. Waktu, seutuhnya milik majikan. Majikanlah yang mengatur kapan mereka (buruh) tidur, makan, dan bekerja. Sementara masyarakat rural, menguasai waktunya sendiri---mereka bebas kapan saja datang ke sawah, kapan tidur, kapan makan, atau kapan bekerja. Maka mudik, menjadi semacam dekontruksi terhadap “waktu majikan” dan menjadikan kepemilikan waktu beralih menjadi “waktu diri sendiri”, atau sinonim dari pemberontakan terhadap kapitaslime. Meski mudik hanya berlangsung beberapa hari saja, ia telah mengubah waktu menjadi ruang, yang barangkali Mark katakan sebagai “ruang pembangunan manusia”. DalamThe Path to Human Development, Capitalism or Socialism, Michael A. Lebowitz menakik Mark, bahwa Seseorang manusia yang tidak memiliki waktu bebas untuk hidup mereka sendiri---yang seluruh waktunya, selain sekadar interupsi fisik seperti tidur, makan, dan sejenisnya, diserap oleh kerjanya untuk kapitalis---tak lebih dari binatang beban. Dari sini, saya berspekulasi bahwa mudik, selain demi perjalanan, juga demi libido pemberontakan terhadap kepemilikan waktu. Keduanya sama dalam satu hal: untuk diri sendiri.Keduanya sama sebagai wujud egosentrisme. Itu berarti, sekalipun di Jakarta Kang Dulkimin berdagang ketoprak---karenanya menjadi “pemilik” waktuitu sendiri, yang berarti waktu tidaklah milik majikan, sebabmajikan adalah Kang Dulkimin sendiri---mudik, pastilah dilakukan demi perjalanan semata. Sungguh, pemudik tak dapat lepas dari jerat keduanya? Tidak bisakah seseorang mudik untuk sesuatu yang di luar dirinya, yang berada jauh di kampung?; demi keluarga, saudara, tetangga, rumah tua, kebun, pekarangan, opor ayam, atau ketupat? Bisakah mudik, tidak lain, berangkat dari perasaan kangen dan cinta terhadap semua itu? Di balik pelepah pisang, saya mendengar bunyi tersedu-sedu. Saya lihat kedua mata Kang Dulkimin berkaca-kaca sambil mengelus nisan mungilnya. Mungkin itu makam anaknya. Hanya sedikit dari tetangga saya yang sekarang mengenal Kang Dulkimin. Saya ingat, Kang Dulkimin tak punya lagi keluarga dan saudara di sini, ia tak punya rumah tua, kebun, pekarangan, atau sekadar opor ayam dan ketupat. Dari sini saya tercekat, barangkali saya keliru mengartikan Mark. Bahwa “ruang pembangunan manusia”, mungkin juga dapat diisi oleh hanya sebuah makam. Jalan-jalan kampung yang dilalui Kang Dulkimin saat ini, sudah banyak berubah. Tetapi oleh segala yang sudah tiada, seseorang dapat berusaha membangun dirinya menjadi manusia. Mereka rela mudik hanya karena sebuah kenangan yang walau tak berbekas, yang tetap dicintai dan dirindui. Kang Dulkimin pun begitu. (*) *Penulis adalah pegiat Komunitas Senja Sastra
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:













