Buku, Razia, dan Hantu Komunis
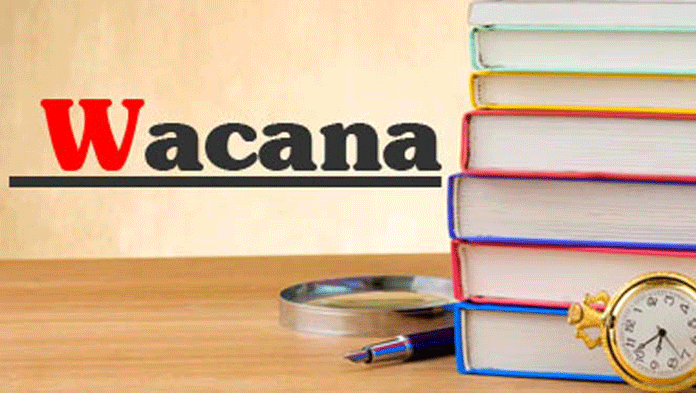
SOAL baca dan buku, saya teringat cerita AS Laksana—penulis buku cerpen Si Janggut Mengencingi Herucakra—membagikan pengalaman batinnya ketika menonton film dokumenter berjudul Fahrenheit 9/11 besutan Michael Moore, peraih penghargaan kategori film terbaik pada Festival Film Cannes 2004. Sulak (panggilan cerpenis cum esais ini) tersentil dengan adegan George W. Bush yang menurutnya tampak dungu saat menara kembar World Trade Center, New York City, tumbang oleh serbuan 11 September 2001. Bush yang tengah asyik membacakan buku untuk anak-anak SD di ruang kelas, ternganga begitu saja setelah mendengar kabar rubuhnya bangunan tinggi itu. Namun, bukan mantan presiden AS yang mencuri fokusnya, melainkan quotes berbahasa Inggris yang terpampang di papan tulis. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih memiliki arti: “membaca membuat negeri kita besar”. Saya tidak ingin membahas filmnya lebih jauh. Hanya menggarisbawahi satu kata penting dari kalimat di atas: membaca. Yang, saya pikir, tidak semua orang mau melakukannya meskipun banyak manfaat yang bisa didapat. Secara sederhana, membaca bisa dikatakan sebagai akivitas melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (buku, koran, surat, majalah, pamflet, flyyer, personal chat, dll). Karenanya, jika ingin cerdas, banyak-banyaklah membaca, jika ingin memiliki segudang pengetahuan, banyak-banyaklah membaca. Jika ingin menjadi manusia yang bermartabat, jangan sekali-kali meremehkan buku. Sekadar contoh, tidak kurang pemberitaan dan informasi mengenai kehebatan bangsa lain yang memperlakukan buku secara layak dan membaca sebagai menu utama. Finlandia misalnya, masih menduduki peringkat negara paling literat. Jepang juga paling sering dibicarakan. Orang-orang muda dan tua mengisi waktu di sela-sela kesibukannya untuk membuka buku, entah di transportasi massal, public space, bahkan toilet. Tidakkah ini menjadi pertanyaan, mengapa mereka gemar sekali membaca buku? Kapan ada waktu dan alasan untuk santai bermalas-malasan? Sependek ingatan saya, sebagian orang masih beranggapan bahwa aktivitas membaca buku tidak memberikan efek apa pun kecuali rasa kantuk. Di antaranya juga merasa bahwa mendapatkan ilmu atau belajar bisa melalui media apa saja. Apalagi di zaman serba gawai, tutorial, dan viral sekarang ini. Belum lagi jika isi buku terlalu serius. Alih-alih mengerti, mengeja cover-nya saja sudah untung. Akhirnya, orang-orang semakin permisif dan tak acuh. Buku cukup dipajang di pojokan lemari dan kita menjadi manusia tsundoku (mengoleksi buku tanpa membacanya), berdebu, sampai suatu saat musnah dimakan rayap. Di sisi lain, membaca buku sering dipandang sebagai bentuk keanehan, kuno, cupu, tidak umum, lekat dengan olok-olok kutu buku, dan kacamata botol. Lebih jauh, sering mendapatkan perbandingan tidak fair. Buku adalah barang mahal. Berat dan tidak efisien dibawa ke mana-mana. Apa guna membeli dan membacanya? Daripada uang dihabiskan demi buku yang hanya dibaca sekali seumur hidup, lebih baik digunakan membeli nasi lengko yang sudah pasti mengenyangkan perut. Wong menutupi kebutuhan sehari-hari saja masih ketar-ketir kok. Apakah buku dapat menyelesaikan kesulitan ekonomi masing-masing orang dan pembacanya? Pertanyaan itu sungguh konyol. Tetapi, saya juga sangsi. Benarkah masih ada kesadaran bahwa buku itu penting dalam ruang lingkup pergaulan sehari-hari? Berapa jam yang disisakan untuk mampir menengok lembar demi lembar halamannya? Jangan-jangan, justru kita lebih banyak meluangkan waktu bermain game, scroll beranda sosmed, dan bergosip. Satu kali dalam sebulan, sempatkah menginjakkan kaki ke toko buku? Ah. Memburu ‘Hantu’ Komunis Sampai di sini, jelas buku bukanlah prioritas. Dan, membaca belum menjadi minat. Jangankan berpikir untuk menabung dan membeli buku, berusaha meminjamnya di perpustakaan-perpustakaan sekolah, kampus, atau daerah saja sangat berat untuk melakukannya. Negara juga tidak cukup hadir dan siap dalam memberikan pemahaman pentingnya membaca dan buku, meski pemerintah menjadikan literasi sebagai salah satu program nasional. Semua terkesan hanya formalitas dan berakhir menjadi slogan belaka. Maka tidak heran, akhir-akhir ini kabar penangkapan sekelompok orang plus merazia sejumlah buku oleh aparat dan yang mengatasnamakan ormas-ormas tertentu di beberapa kota kembali menghangat. Buku-buku yang menjadi incaran adalah yang berbau paham komunis atau lazim disebut berhaluan kiri. Hal ini, menurut saya, seolah memosisikan buku sebagai terdakwa dan semakin jauh dari fungsinya. Buku justru dianggap sebagai sumber konflik. Semakin terintimidasi lantaran ada penggolongan dan pelarangan untuk dibaca dan dikaji. Peredarannya dibatasi, dipantau, dan lebih berbahaya dari narkoba, ditakuti, pemicu non-konformitas yang mengancam ketertiban umum. Juga banyak forum-forum diskusi yang dicekal atau dibubarkan. Sampai kemudian, aksi penyensoran buku secara sepihak dianggap sebagai langkah paling tepat. Apakah sejarah paranoid massal dan pemberangusan kala rezim Orba akan terulang? Putusan MK No. 20/PUU-VIII/2010 yang mencabut UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak menemui titik temu. Teror dan kekhawatiran negara terhadap jenis buku tertentu terkesan seperti mengejar-ngejar arwah penasaran yang memiliki dendam kesumat. Hal itu memicu kegaduhan yang, menurut saya, sia-sia. Bukankah membaca dan memperoleh pengetahuan adalah hak setiap orang? Proses seseorang mengkaji dan memahami bacaan tidak lantas sekonyong-konyong kemudian dihubung-hubungkan dan diperhadapkan dengan situasi rezim tertentu. Apa sesungguhnya yang ditakutkan? Sebagai produk pikiran, memang tidak semua buku berkualitas. Tetapi juga tidak semua otak pembaca dapat memahami dengan baik maksud yang tertulis di dalamnya. Sederhananya, butuh proses pembelajaran dan kajian yang tidak sebentar untuk menelaah. Adapun buku-buku ‘terlarang’ tersebut dijadikan rujukan dalam bersikap oleh pembacanya adalah soal lain. Paling tidak, ada cara-cara lebih elegan yang bisa ditempuh. Tidak main grebek, tangkap, ciduk, rampas, yang ujungnya justru menimbulkan kebencian, menyalah-nyalahkan, dan trauma terhadap buku-buku tertentu. Artinya, masih banyak orang yang belum memahami bagaimana berpikir dan bersikap ilmiah. Dalam perguruan tinggi, buku-buku itu dipelajari. Sehingga menurut dosen dan akademisi bahasa Indonesia, Yunus Abidin, membaca memerlukan strategi. Ibarat sopir, akan kebingingungan dan frustrasi jika tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengetahui alamat yang dituju. Seorang pembaca yang hanya dapat memahami rangkaian huruf akan mengalami kesulitan karena tidak dapat memahami makna yang terkandung dalam bacaan. Selanjutnya, akan putus asa dan enggan untuk membaca kembali. Pembaca semacam ini hanya menghabiskan waktu dengan percuma (Strategi Membaca, 2010: 3). Disadari maupun tidak, bukankah aksi perampasan terhadap buku merupakan kemunduran berpikir? Sudah berapa banyak buku dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan (politis) segelintir orang? Berapa banyak buku karya penulis-penulis hebat bangsa ini yang justru bermukim di negara lain dan sulit membawanya kembali yang mestinya dijaga, dirawat, dan diarsipkan sebagai dokumentasi otentik berbagai rujukan ilmu, pengetahuan, dan saksi peristiwa? Lantas, melalui apa kita mengenal keberanian Wiji Thukul dalam menentang pemerintahan yang sewenang-wenang kalau tidak dengan membaca buku? Thukul adalah cerita penting dalam sejarah Orde Baru. Seorang penyair yang sajak-sajaknya menakutkan sebuah rezim diktator. Pada peristiwa kerusuhan 1998 namanya disebut-sebut dalam DPO, oleh polisi dan tentara dicap sebagai ‘Setan Gundul’. Tapi, tiba-tiba saya ingat ucapan seorang kawan dari penerbitan, bukankah buku sudah tidak laku? (*) *Penulis bergiat di Ngopi Rabu Malam komunitas sastra Lingkar Jenar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:










