Santri dalam Historiografi: Berdaya-Berbudaya
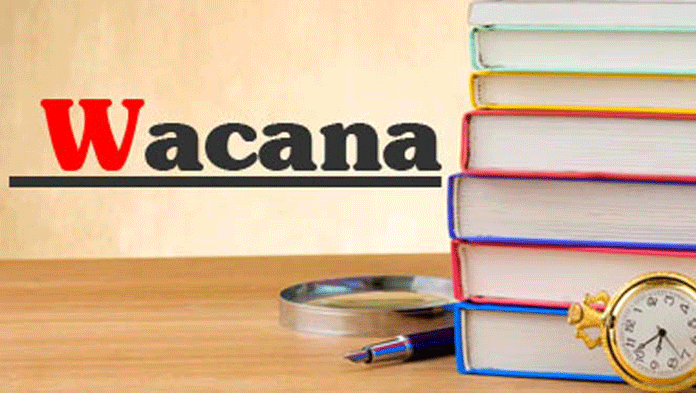
Oleh: DR Eva Nur Arovah*
22 Oktober kemarin menjadi peringatan ke-6 Hari Santri Nasional. Momentum yang dirayakan secara nasional ini sekaligus menandai realitas sejarah suatu kelompok masyarakat yang kelak membentuk “Tradisi Besar” santri.
Termonologi “santri” dengan demikian tidak melulu diartikan sebagai orang-orang yang ada di lingkungan pesantren sebagai tempat para santri menimba ilmu agama, bersama unsur-unsur pelengkap lainnya: kiai, kitab-kitab klasik, dan masjid.
Karena jika dilacak lebih jauh, akar tradisi santri pada hakikatnya merupakan konstruksi sosial berbasis agama yang menjadi ujung tombak penggerak Islam (terutama) Jawa dengan spektrum cakupannya yang luas serta lahir bersamaan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia.
SANTRI: BERDAYA-BERBUDAYA
Anak judul di atas merupakan representasi dari kekuatan, kemampuan, juga cara yang dimiliki santri dalam mengatasi berbagai persoalan dan mencari solusi bagi berbagai kebuntuan. Santri juga menjadi kelompok yang mampu menciptakan sejarah, peradaban dan kebudayaan sekaligus pelaku kebudayaan dan peradaban itu sendiri.
Yang demikian ini serupa dengan membaca ulang posisi strategis santri dalam realitas kehidupan ketika bersentuhan dengan fenomena sosial, politik, ekonomi, serta kebudayaan. Historiografi Indonesia menyebutkan istilah yang merujuk pada betapa berdaya-berbudayanya santri yaitu Santri Dagang, Santri Kelana dan kaum “Putihan” (Lombard: 2005).
Istilah Santri Dagang (Geertz: 1981) merujuk pada struktur sosial santri yang intinya berpusat di tempat perdagang atau pasar. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat Islam hadir di Nusantara (baca: Indonesia) melalui jalur-jalur pelayaran antarbenua.
Pelayaran bagi bangsa Arab sebagai pedagang sekaligus penyebar agama Islam sudah menjangkau banyak belahan dunia, bahkan pada wilayah yang belum dikenal bangsa lain. Kontak dengan peradaban Islam yang terjadi berabad-abad lalu tersebut bukan hanya melahirkan agama baru melainkan membawa serta kekuatan baru dalam bidang ekonomi.
Pada tahap inilah spirit dagang muncul beriringan dengan perkembangan agama Islam terutama di kawasan pesisir. Pesisir yang metropolis, pusat-pusat penyebaran Islam terbentuk di kawasan pantai Sumatera, Jawa, hingga Nusantara melahirkan masyarakat heterogen: nelayan, pelaut, pedagang, kuli pengangkut, penyebar agama hingga petualang membaur satu sama lain membentuk jaringan niaga yang kuat.
Dari semua kawasan pesisir yang menjadi pusat penyebaran Islam tersebut, pesisir utara Jawa memiliki ciri khas tersendiri dengan kehadiran Wali Sanga di Cirebon, Demak, Kudus, Tuban, Gresik, Lamongan, Surabaya.
Tidak boleh dilupakan peran yang dipegang Banten, Pemalang, Pati, Jepara, Pekalongan dan kota-kota pesisir lainnya. Tome Pires dalam Suma Oriental (2015) melaporkan bahwa dia menyaksikan para ulama abad ke-16 sangat aktif menjalankan perdagangan, membaur dengan masyarakat dan budayanya, mengajarkan sastra, ilmu pertukangan, perikanan, pelayaran, arsitektur, seni ukir, batik, kaligrafi, musik, dan lainnya.
Dengan kata lain Islam yang hadir dengan elsatis membawa serta sentuhan estetik seraya mengalami proses “indonesisnisasi” (Kuntowijoyo, 1995) bahkan mampu melahirkan varian kebudayaan Islam baru di luar tanah kelahirannya.
Lebih jauh lagi para wali juga mendirikan dan membina lembaga-lembaga pendidikan sebagai cikal bakal pesantren yang berkembang semenjak abad ke-16. Bukan sebatas lembaga pendidikan agama, secara kultural pesantren menjadi kunci dalam penciptaan kelompok masyarakat yang dinamai “santri” atau golongan muslim yang taat beribadat (putihan) juga sebagai tempat yang dapat memberikan kekuatan spiritual sekaligus sumber inspirasi bagi sikap hidup yang tenang dan tentram.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:










