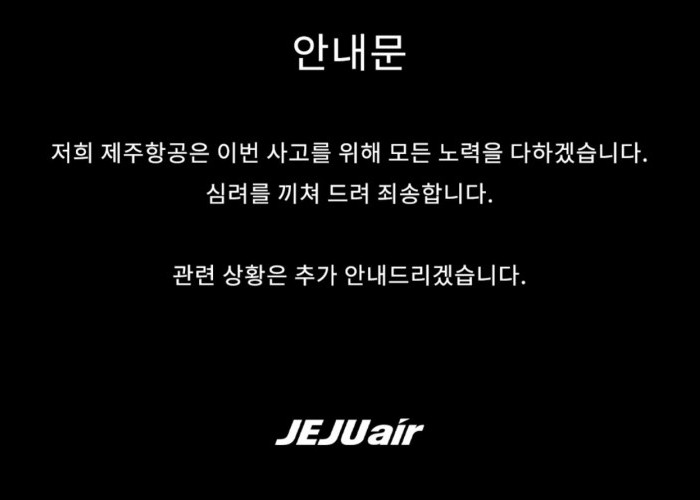Peran Sosial Agama dalam Isu Timteng
MEMERHATIKAN jalannya proses revolusi di Timur Tengah, baik di Mesir, Lybia, Palestina, Afghanistan, Maroko, Aljazair, Sudan, Irak ataupun di Iran belakangan ini, rasanya kita patut bertanya, di manakah sesungguhnya fungsi dan peran agama-agama? Sebagai motivator, aktor, ataukah sebagai “pemain pengganti” dari game proses revolusi? Jawaban atas pertanyaan ini penting karena ia akan menjadi ketentuan mutlak bagi diskursus keagamaan di masa kini dan mendatang, dalam kaitan posisi agama di ruang publik (ranah politik). Dengan sendirinya, masalah revolusi Timur Tengah secara sosiologis akan terkait dengan pertanyaan mengenai peran agama dalam politik. Kita adalah generasi yang beruntung karena sempat menyaksikan bagaimana gonjang-ganjing memanasnya isu di Timur Tengah, sekaligus bisa membuat semacam evaluasi dan gambaran tentang sikap yang harus dilakukan bangsa Indonesia menanggapi isu yang sama. Hal ini merupakan suatu keniscayaan bagi kita untuk menjadi generasi yang benar-benar sadar akan peran sejarah. Demokratisasi politik Timur Tengah agaknya tidak bisa dimundurkan lagi. Kenyataan ini dapat dilihat dalam perkembangan politik di Timur Tengah menyusul jatuhnya Husni Mubarak (Presiden Mesir). Hal ini menandai telah berlangsungnya proses transisi ke arah demokrasi, setelah demokrasi Mesir terpenjarakan 31 tahun lamanya. Akan tetapi harus segera dikemukakan, sejak kejatuhan Mubarak, belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan (conincing sign), yang mengindikasikan transisi yang sedang berlangsung dapat benar-benar berhasil mewujudkan demokrasi otentik. Menurut pandangan Ibn Khaldun, setelah suatu negara mencapai puncak kejayaan, negara kemudian akan mengalami keadaan yang “stabil” untuk kemudian mulai mengalami guncangan dan disintegrasi. Hal ini dikarenakan bahwa penguasa dan masyarakat lebih tertarik untuk menikmati hidup dengan kemewahan. Pada beberapa sub bahasan dalam Mukadimah dan Kitab al-Ibar Ibnu Khaldun menjelaskan masa pertumbuhan, kemajuan dan kemunduran negara adalah 120 tahun. Yang terbagi ke dalam tiga generasi manusia, sehingga persisnya dalam tiap generasi masing-masing 40 tahun. Jika jangka waktu yang dipaparkan Ibn Khaldun diterapkan pada masyarakat Timur Tengah, maka ia banyak benarnya. Setelah melewati masa pertumbuhan, kemajuan dan kemunduran pada masyarakat Timur Tengah telah menunjukan indikasi apa yang menjadi gagasan mendasar dari Khaldun. Meningkatnya absolutisme penguasa-penguasa Timur Tengah, berbarengan dengan sikap hedonisme, melonggarnya keberpihakan terhadap rakyat, memperkaya diri, dan dari semua akan bermuara pada meningkatnya disintegrasi sosial dan politik. Disinilah perlunya revitalisasi dengan melakukan koreksi total terhadap berbagai aspek budaya peradaban. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Liga Arab atau organisasi yang bernafaskan Islam cukup serius dan sungguh-sungguh untuk melakukan koreksi total tersebut? Jika tidak, proses disintegrasi sosial dan politik di Timur Tengah semakin sulit diatasi. Belum terwujudnya stabilitas politik di Timur Tengah yang krusial bagi pemulihan stabilitas keamanan, bukan hanya disebabkan kontroversi dan reporkusi politik yang semakin memanas, tetapi juga karena elite politik Timur Tengah dan banyak kalangan masyarakat belum siap dengan transisi demokrasi dan budaya politik baru yang lebih demokratis. Di sinilah perlunya peranan agama di dalam proses revolusi Timur Tengah. Apabila ini dilakukan, maka dalam jangka panjang kemungkinan besar agama masih akan memiliki legitimasi karena memang mempunyai saham dan andil besar untuk ikut memainkan peranannya dalam panggung politik di Timur Tengah. Akan tetapi jika agama tidak mempunyai fungsi vital dalam proses revolusi, sementara hampir semua mata dunia melihat bahwa proses revolusi Timur Tengah merupakan babak baru dalam mengubah haluan sejarah perpolitikan, maka dalam jangka panjang agama akan kehilangan legitimasinya untuk berperan dalam politik. BUDAYA DEMOCRATIC CIVILITY Kekuatan masyarakat yang bersatu dalam menggulingkan pemerintahan telah banyak terbukti. Muammar Qaddafi (Libya), Husni Mubarak (Mesir), Zaenal Abidin bin Ali (Tunisia), Sultan Qaboos bin Said (Oman) adalah sederet nama pemimpin Timur Tengah yang digugat rakyatnya. Bila melihat ukuran dorongan dari masyarakat bawah dan maraknya aksi unjuk rasa, dapat diperkirakan proses disintegrasi negara-negara Timur Tengah akan terus menyebar seperti virus yang mematikan. Meminjam istilah Robert Hafner (1998), Keadaban Demokratis (Democratic Civility), bahwa untuk mengatur jalannya pemerintahan, negara harus kuat tetapi sekaligus self-limiting dalam artian tidak memonopoli seluruh kekuasaan masyarakat dan sekaligus menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Diperlukan pengembangan budaya politik yang pro rakyat, yang mampu mewadahi orientasi politik para pemimpin dan warga negara. Dalam ungkapan lain Azyumardi Azra (1999) mengatakan bahwa wacana publik tentang revolusi dan pengembangan budaya politik, bermuara pada gagasan tentang pembentukan masyarakat madani. Menurut Azra, sebagian ahli bertitik tolak dari kerangka dan pengalaman Eropa Timur dan Amerika Latin yang memandang bahwa masyarakat madani dalam posisi oposisional vis a vis negara, dan bahkan sebagai alternatif bagi negara. Karena seperti dikemukakan Hafner, pengembangan keadaban demokratis sangat tergantung pada perubahan dan penyesuaian kultural dan institusional. Apabila kita amati fenomena gerakan protes yang terjadi di Timur Tengah, sebenarnya adalah refleksi dari ketidakmampuan pemimpin negara untuk memberikan kesejahteraan publik yang terpinggirkan. Hal ini diperparah dengan ketertindasan yang dihadapi oleh umat Islam, baik oleh kekuatan Barat maupun oleh pemimpinnya sendiri. Terlepas dari realitas politis tersebut, fenomena ini sebenarnya juga mengandung jebakan-jebakan. Pertama, jangan-jangan disintegrasi di Timur Tengah merupakan rekayasa politik global untuk memecah belah masyarakat Arab yang notabenya adalah masyoritas beragama Islam. Kedua, negara-negara Timur Tengah telah kehilangan bingkai kebersamaan atau komitmen kebangsaan untuk berusaha mewujudkan kemakmuran dan kesejahtraan. Kalau itu yang terjadi, maka kemudian agama telah menjadi instrumen partikularistik gerakan-gerakan agama dan kebangkitan kelompok yang kemudian mendapatkan angin segar dari suara-suara internasional yang menginginkan perpecahan di dunia Islam. Hal ini yang diperlukan oleh negara, agar agama dijadikan perekat pada level society. Jika perekat itu hilang dan diganti oleh ikatan kepentingan salah satu golongan, maka konsep kenegaraan yang memiliki budaya democratic civility akan lenyap secara perlahan. Apabila Timur Tengah berhasil menuntaskan agenda revolusi dan membangun kembali pemerintahan yang konsisten untuk mensejahtrakan rakyatnya, maka masyarakat Timur Tengah sedang dibawa ke suatu masa depan gemilang. Namun, apabila proses revolusi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, semua protes sosial yang dilakukan masyarakat Timur Tengah dikhawatirkan akan menjadi bumerang. Setidaknya ada beberapa harapan masyarakat Timur Tengah dari banyaknya tuntutan yang mereka lakukan. Pertama, normalisasi proses demokrasi. Kedua, peningkatan kesejahtraan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Ketiga, pengembangan dan pemberdayaan kaum intelektualitas dan profesional di segala bidang. Keempat, hubungan internasional yang lebih progresif untuk kemajuan negara. Kelima, sosialisasi pendidikan ketatanegaraan. Apabila semua aspek tersebut dilaksanakan oleh pengemban amanah kepemimpinan, harapan untuk membangun keadaban demokratis seperti gagasan Hafner, mungkin bisa terwujud. (*) Penulis, Kaprodi Pendidikan Sejarah Kampus Putih Indramayu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: