Menyoal Gerakan Literasi di Cirebon
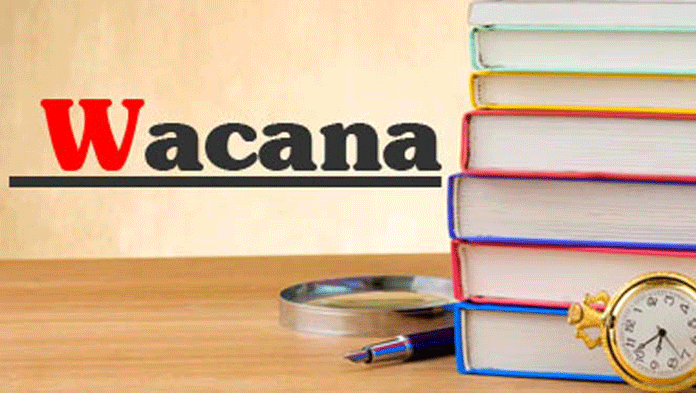
Oleh: Adam Sudewo
SULIT bagi saya untuk mempercayai bahwa nasib manusia sepenuhnya berada di tangan Tuhan yang menebarkan bakat, kecerdasan intelektual, kecakapan dan ketidakcakapan literer dalam diri manusia yang sama sekali baru.
Saya juga sulit percaya jika intelektual adalah mereka yang dipilih secara acak dan merupakan wakil dari dewa, reinkarnasi orang suci, atau bangsawan. Daripada Julian Benda yang mengidentifikasi sosok intelektual sebagai segelintir manusia sangat berbakat dan yang diberkahi moral filsuf-raja, saya lebih mempercayai Gramsci yang dalam Prison Notebooks menulis bahwa “Semua manusia adalah intelektual, tetapi tidak semua manusia memiliki fungsi intelektual.” Pendek kata, saya tidak percaya pada gerakan literasi saat ini.
Kerja intelektual adalah kerja literer. Dan karenanya perlu literasi. Walaupun di zaman di mana manusia diukur dari apa yang ia konsumsi, literasi berkembang bukan hanya menyoal buku dan tulis-menulis. Pada tahun 2015, World Economic Forum menyatakan enam literasi dasar yang meliputi literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan.
Tetapi tetap saja, literasi memiliki biografi samar. Apa dan bagaimana proses serta tujuan literasi bahkan kian ke sini kian gelap. Dan ini membuat saya tak mempunyai keberanian untuk memproklamirkan diri sebagai pegiat literasi, apalagi membentuk kelompok dengan embel-embel literasi sebagai “simbol” yang dikonsumsi publik.
Jika boleh jujur, persoalan literasi adalah persoalan berat bagi saya. Setiap kali mencoba lari darinya, saat itu juga ia menjerat dan melilit tubuh saya layaknya makanan laba-laba. Sampai suatu saat seorang teman datang membawa pisau untuk mengiris benang tersebut dan membuat saya terbebas.
Ia berkata bahwa literasi adalah pikiran yang melek, terjaga—dinamika dan dialektika yang pertama-tama berlangsung di dalam kepala. Oleh karena itu, kegiatan literasi sama sekali bukanlah kegiatan penuh bedak demi mendapatkan status sosial. Bukan juga tempat untuk membuat seseorang terperosok dalam kubangan romantisme.
Kegiatan literasi, adalah sebuah pergulatan subyek-subyek dalam bersentuhan dengan realitas yang kini didominasi simulasi, di mana segala sesuatu tampak mengambang namun kemudian hadir sebagai realitas kedua dengan rujukan dirinya sendiri. Baudrillard menyebutnya sebagai hiperrealitas.
Sebuah proses literasi bisa tercapai jika syarat berikut terpenuhi: seseorang rela membaca dan menyediakan tempat bagi kesadaran kritis di kepalanya sebagai upaya untuk membebaskan diri dari kesadaran naif dan kesadaran magis. Menurut sosiolog C. Wright Mills dalam konsep sociological imagination tentang kesadaran kritis, imajinasilah yang dapat membantu seseorang memahami pengalaman hidupnya dengan struktur sosial di masyarakatnya.
Walaupun prosesnya bisa dilakukan secara berkelompok, misalnya saja mendirikan komunitas literasi, tetapi muara literasi adalah menciptakan individu-individu yang tidak terkonstruksi, terhegemoni, apalagi terdominasi oleh wacana dan simbol apa pun yang tidak literer. Dengan kata lain, individu literer adalah ia yang cakap membaca realitas, struktur sosial, dan menempatkan diri dengan keberpihakan yang emansipatoris. Goals komunitas literasi tidak diukur dari kesuksesan acara yang digelarnya, melainkan sejauh mana individu di dalamnya bisa membaca dengan kritis berbagai fenomena seperti kemiskinan, penderitaan, rasa sakit, kejahatan, dan lain-lain.
Sayangnya gerakan-gerakan literasi di Cirebon lahir dari kelatahan sebagaimana publik di tanah air mendadak pernah mengalami demam telenovela, demam sinetron, demam Korea, hingga demam tiktok dan demam-demam lainnya. Hal tersebut bisa kita lihat dari berbagai ritus literasi yang “asal bunyi” dengan sikap dan hasrat yang begitu sadar kamera.
Tidak mengherankan jika kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan literasi, alih-alih mengedepankan bobot dan substansi, justru memprioritaskan target “instagramable” meski sebetulnya hanya delusi.
Sepanjang pengamatan saya selama dua tahun terakhir, saya melihat para pegiat literasi gemar sekali melakukan reduksi murahan dan menjijikkan. Sastra disimpulkan sebagai bukan kegiatan literasi dan hanya sebatas hiburan yang nir pengetahuan, kajian sejarah hanya menjadi obyek yang diingat dalam kesadaran timeline, dan sosok besar dan revolusioner seperti Tan Malaka diringkus menjadi akal-akalan enterpreneurship.
Lalu pada saat yang sama, saat khatam membaca buku Soekarno dan Machiavelli, para pegiat literasi merasa sudah mengerti filsafat politik. Saat khatam membaca satu buku Bung Hatta, merasa sudah melewati proses panjang pendidikan karakter.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:












