Menyoal Gerakan Literasi di Cirebon
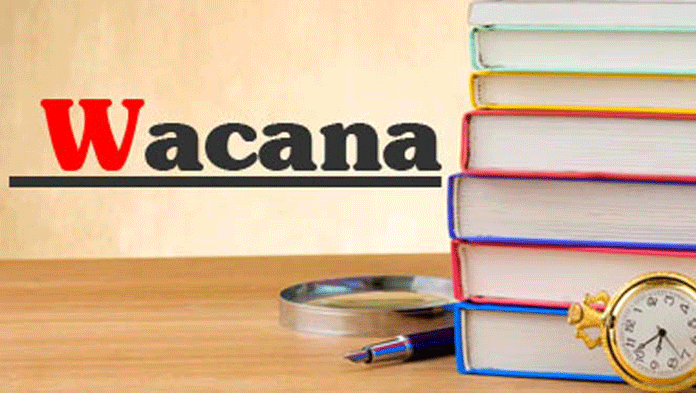
Saat khatam membaca catatan Soe Hok Gie, merasa sudah menjadi aktivis idealis. Saat khatam membaca buku persahabatan Sukarno dan Kennedy, merasa sudah menguasai ilmu politik internasional. Saat sudah pernah mengundang seleb literasi, merasa sudah beres sebagai gerakan literasi.
Parahnya lagi, semua reduksi dikemas dalam unggahan media sosial dengan quote dan caption yang kelewat berantakan.
Menjadi mudah dimengerti jika maraknya gerakan literasi di Cirebon, tidak dibarengi dengan munculnya individu-individu literer. Kajian lokalitas, konstruksi dan dekonstruksi budaya, dinamika seni dan tradisi, historiografi, evaluasi kebijakan publik, semua seakan di luar jangkauan literasi. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Namun itu bisa dihitung tanpa menggunakan jari.
Namun jika benar komunitas-komunitas literasi justru menjadi sarang kebebalan dan produsen hipperralitas, lalu kenapa ada banyak pemuda-pemudi yang menggandrungi? Kenapa meski tanpa tunjangan dan gaji, orang-orang rela mendaftarkan diri dengan menempuh seleksi dengan metode interogasi? Bahkan saat sudah ada di dalamnya, mereka berbangga mengenakan busana seragam layaknya karyawan perusahaan atau siswa-siswi yang tengah magang di lembaga atau instansi.
Fenomena ini bisa dipahami dengan kerangka berpikir Baudrillard soal manipulasi tanda yang lahir dari mode of consumption. Simbol-simbol memang bersifat manipulatif. Seseorang bisa benar-benar membutuhkan pakaian bermerek saat ia menghendaki simbol-simbol yang berorientasi pada status sosial.
Dan kita melihat betapa arus besar media sosial memang mengarah pada itu. Apalagi di era posttruth ini, citra semakin menjadi yang dikonsumsi sekaligus diproduksi.
Menggunakan terminologi Yasraf Amir Piliang, fakta hari ini adalah realitas yang telah dilipat-lipat sedemikian rupa sebagai konsekuensi dari hadirnya teknologi mutakhir terutama transportasi dan telekomunikasi. Hal ini berakibat pada pemadatan ruang-waktu dan informasi. Yang maya dan yang nyata menjadi kabur. Citra bergeser menjadi kenyataan. Dan sebaliknya, kenyataan bisa dianggap sebagai citra. Hingga pada saat komunitas-komunitas literasi hanya diisi oleh para pesolek, orang-orang yang seumur hidupnya bergulat dengan teks dan peristiwa, justru tidak pernah memproklamirkan diri sebagai pegiat literasi dan karenanya mungkin sekali tidak dianggap sebagai aktor literasi.
Namun di sana, di tiap “gerombolan” yang mengatasnamakan gerakan literasi, setidaknya ada etalase yang menyediakan dan mempertontonkan simbol-simbol intelegensi, intelektualisme, kepandaian, dan segala kecakapan otak yang bisa didapat dari pengobralan kata “literasi”. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa komunitas-komunitas literasi di Cirebon saat ini lebih mirip supermarket dan pegiatnya adalah kerumunan konsumen yang wajahnya tertutupi spanduk diskon dan iklan.
Tegasnya, komunitas literasi adalah tempat di mana realitas semu dilipatgandakan. Idealisme diobral, namun dengan penuh jemawa membuang esensi literasi demi mendapat banyak anggota.
Jika sudah begini, lalu apakah gerakan literasi khususnya di Cirebon layak diperhitungkan? Apakah gerakan literasi bernilai positif terutama dalam menghadapi realitas yang sudah dilipat-lipat ini?
Untuk sementara ini, saya terpaksa harus menyebut bahwa gerakan literasi yang ada, justru telah mengakibatkan kebangkrutan intelektual. Sebab alih-alih menciptakan kesadaran kritis sebagaimana disebut di muka, gerakan literasi di Cirebon malah gemar melakukan reduksi dan pemalsuan-pemalsuan realitas lewat berbagai sebaran di media sosial.
Di tangan merekalah, kini arti literasi bertransformasi hanya menjadi fashion dan pemenuhan identitas. Literasi bukan lagi menjadi alat pembebasan dan pencerahan, melainkan sebuah mode baru untuk mendapatkan secara instan status seleb literasi.
Namun ada sejumlah cara bagi komunitas-komunitas literasi di Cirebon agar tidak memberi kontribusi negatif pada kehidupan publik di kota ini. Salah satu yang paling gampang adalah berhenti beraktifitas atau membubarkan diri.
Sebab paling tidak, itu akan membuat simulakra dan sampah digital menjadi sedikit berkurang. Atau sedikitnya tidak turut membuat kata “literasi” menjadi lebih busuk, sebagaimana kata “senja” yang hari ini sudah sedemikian bopeng, pasaran, dan sebagai kata telah kehilangan makna dan getarannya. (*)
*Penulis adalah pegiat Tjirebon Book Club
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:









