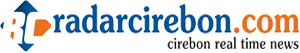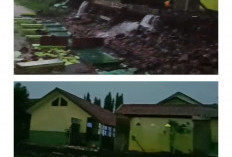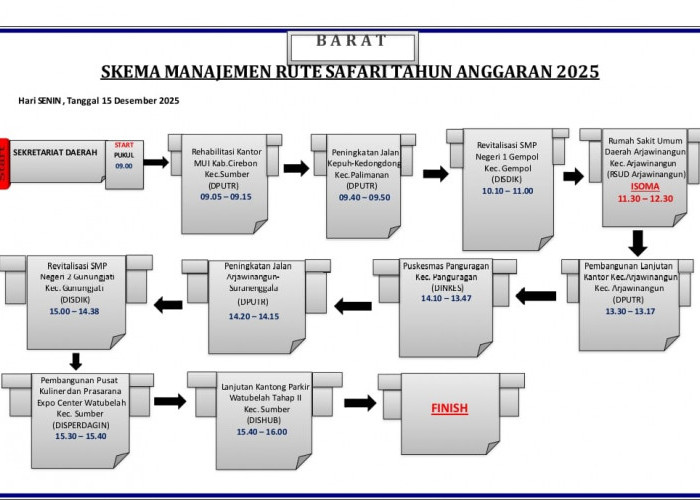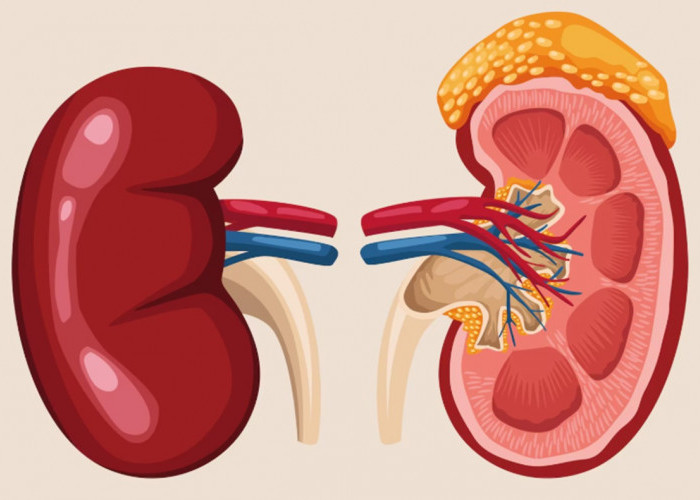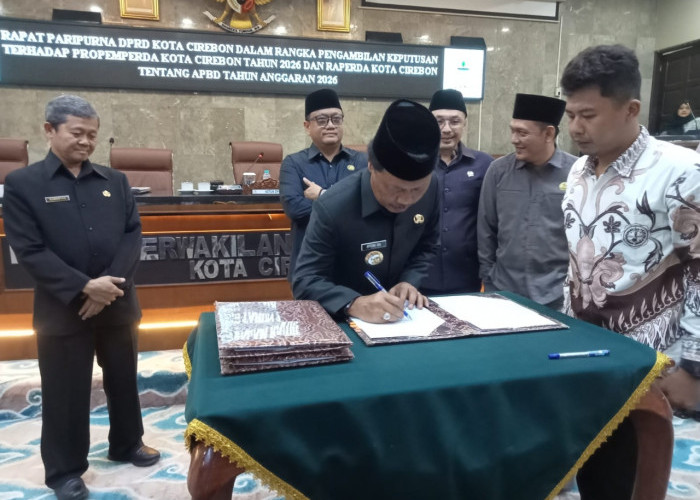One Health: Strategi 'Gotong Royong' Dalam Peta Jalan Isu Kesehatan Pasca-pandemi

dr. Ahmad Fariz Malvi Zamzam Zein, SpPD, FINASIM, FACP-Istimewa -
RADARCIREBON.COM - Presiden RI, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tertanggal 22 Juni 2023, menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia dan mengubah status COVID-19 sebagai penyakit endemi.
Keputusan ini didasarkan pada beberapa hal, yakni penurunan kasus penderita dan keparahan COVID-19 di Indonesia secara signifikan dan kemampuan dalam mengatasi kondisi pandemi baik dalam tata kelola masyarakat melalui pelbagai upaya kesehatan masyarakat hingga pelaksanaan vaksinasi maupun peningkatan kapasitas layanan dan fasilitas kesehatan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 mulai dari skrining, diagnosis, pengobatan, hingga upaya rehabilitatif atau pemulihan.
Seiring dengan dengan Keppres ini, maka status COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional nonalam juga dicabut.
Namun, kita ketahui bersama, belakangan ini beberapa negara, termasuk negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, melaporkan kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan seiring dengan temuan varian virus SARS-CoV-2 yang baru (EG.5 dan HK.2) yang masih merupakan strain virus Omicron.
BACA JUGA:Banyak Mobil Wisatawan Selip Kopling, Polisi Sigap Dorong Mobil Mogok
Bahkan, dalam beberapa waktu lalu pula, kasus COVID-19 mulai dilaporkan di Jakarta. Tentu kita tidak berharap pandemi berulang, bukan? Lalu, bagaimana peta jalan kita dalam menanggapi dan membangun kesiapsiagaan terhadap potensi pandemi dan penyakit yang merebak di masyarakat?
Menilik kembali pandemi vs endemi
Center of Disease Control (CDC) mendefinisikan lonjakan masalah kesehatan masyarakat dalam beberapa istilah, yaitu epidemi, pandemi, dan endemi. Epidemi diartikan sebagai lonjakan kasus penyakit yang mendadak dan melebihi prediksi yang terjadi pada masyarakat di daerah tertentu.
Penyakit yang pernah menjadi epidemi adalah Ebola di Republik Demokratik Kongo tahun 2019, flu burung (Avian influenza) di Indonesia pada tahun 2012, dan severe acute respiratory syndrome (SARS) pada tahun 2003.
Wabah memiliki pengertian yang sama dengan epidemi, namun seringkali digunakan untuk lingkup geografis yang lebih terbatas. Pandemi adalah suatu epidemi yang menyebar di banyak negara atau benua dengan berdampak pada temuan kasus yang banyak.
Endemi merujuk pada adanya temuan kasus penyakit yang relatif konstan atau kemunculan penyakit yang biasa ada pada suatu masyarakat dalam daerah geografis tertentu, misalnya demam berdarah dengue.
BACA JUGA:Ternyata Ini Alasan Kevin Diks Rela Tinggalkan FC Copenhagen Demi Gabung Borussia Monchengladbach
Berbeda dengan pandemi yang penyebaran penyakitnya berdampak luas secara secara geografis dan terjadi secara serentak bersamaan, temuan kasus pada endemi bersifat konstan dan dapat diprediksi dengan cakupan area meliputi satu daerah geografis.
William Schaffner, pakar penyakit infeksi dari Vanderbilt University Medical Center di Nashville, memaparkan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan status endemi dapat diberlakukan.
Pertama, tingginya imunitas (kekebalan tubuh) masyarakat. Kondisi dapat dilihat melalui angka cakupan vaksinasi COVID-19 masyarakat dan rendahnya kasus COVID-19 baru. Tidak didapatkannya kasus dalam klaster tertentu juga turut memperkuat poin pertama ini.
Kedua, kemampuan fasilitas dan layanan kesehatan yang adekuat dalam penanganan kasus COVID-19. Tentunya ini dapat dilihat pada tidak ditemukannya lagi kondisi krisis dan kritis di fasilitas kesehatan dalam penanganan COVID-19, mulai ketidaktersediaan vaksin, tes skrining/diagnosis COVID-19 (seperti tes Antigen atau tes PCR COVID-19), obat-obatan, atau bahkan oksigen dan ruang rawat isolasi. Dampak kolateral dari poin kedua ini adalah kondisi perbaikan pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat.
Ketiga, kemunculan varian-varian virus penyebab COVID-19, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), yang baru bermanifestasi sebagai penyakit dengan kondisi yang lebih ringan.
Kondisi ini terlepas dari apakah disebabkan oleh kekebalan masyarakat yang sudah terbentuk, varian virus yang menyebabkan perubahan pada virus (mutasi) namun berdampak pada virus menjadi lebih 'lemah' dan tidak mematikan, atau keduanya.
BACA JUGA:Pagar Laut Milik PT TRPN di Bekasi Langgar Tata Ruang, Pemprov Jabar Layangkan Surat Teguran
Profesor Aris Katzourakis, pakar evolusi virus dan genomik dari University of Oxford, Inggris, menulis artikel di jurnal Nature yang rilis pada 24 Januari 2022 dengan judul COVID-19: endemic doesn't mean harmless.
Hal senada disampaikan pula oleh Robert Sinto, pakar penyakit tropis dan infeksi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - RSUPN Cipto Mangunkusumo, pada artikel di jurnal Acta Medica Indonesiana terbit November 2022 berjudul COVID-19 pandemic-to-endemic transition in Indonesia: what does the future hold?
Artikel-artikel tersebut menunjukkan kegelisahan para pakar terkait terhadap miskonsepsi bahwa endemi merupakan akhir dari kondisi berbahaya atau berisiko bahaya. Terlebih lagi, istilah endemi ini menjadi sebuah excuse bagi pemangku kebijakan di pelbagai negara untuk berbuat sedikit atau bahkan tidak ada aksi yang dilakukan untuk melakukan upaya mitigasi dan penanganan pandemi-endemi.
Malaria yang menyebabkan kematian lebih dari 600.000 orang dan 1,5 juta orang meninggal karena tuberkulosis pada tahun 2020. Jelasnya, perubahan status endemi tidak serta merta mengubah hidup menjadi 'normal' dan in toto terbebas dari COVID-19. Apakah memungkinkan munculnya kembali pandemi COVID-19? Atau apakah akan muncul pandemi penyakit baru?
Bagaimana epidemi-pandemi terjadi?
Hubungan antara manusia, hewan, dan lingkungan itu terikat dan terkait (interlinkage). Hal ini juga turut digambarkan dalam trias epidemiologi yakni manusia sebagai pejamu (host), virus, bakteri, dan lain-lain sebagai penyebab (agent) yang pada beberapa penyakit turut dibawa oleh perantara seperti hewan, dan faktor lingkungan (environment).
BACA JUGA:Wahidin Scout Games 6 Diikuti Ratusan Peserta
Interaksi ketiganya berdampak pada kemunculan dan tingkat keterkendalian suatu penyakit yang menjadi epidemi atau bahkan pandemi, yakni wabah penyakit yang pernah menjadi wabah (re-emerging disease), penyakit yang sudah ada muncul sebagai wabah baru (newly emerging disease), atau bahkan penyakit yang benar-benar baru (X disease).
Penularan dari manusia ke manusia dapat terjadi melalui satu atau lebih dari empat mekanisme dasar, yaitu pernapasan, saluran cerna, penyebaran lingkungan melalui kondisi perantara lingkungan (makanan, air), dan penyebaran lingkungan melalui inokulasi (vektor seperti nyamuk).
Mekanisme penularan ini menunjukkan hubungan dengan perilaku sosial manusia (seperti perilaku menjaga sanitasi, cara berpakaian dalam konteks menutupi bagian tubuh yang berisiko kontak dengan sumber penularan, dan perilaku seksual) dan bagaimana manusia atau masyarakat berinteraksi dengan lingkungan (seperti penyimpanan dan pembuangan makanan atau minuman dari berbagai sumber, pengelolaan makanan atau bahan makanan).
Keberagaman biologis (biodiversity), yang mencakup keberagaman makhluk hidup dan kompleksitas ekologi, turut terganggu dalam munculnya pandemi, termasuk pandemi COVID-19. Kelangkaan spesies organisme tertentu yang makin meningkat akan mengubah pola penggunaan alam (seperti lahan dan laut) yang berdampak pada hilangnya habitat organisme tertentu dan perubahan iklim.
BACA JUGA:Segini Harga Pasar Kevin Diks Usai Resmi Dipinang Borussia Monchengladbach
Ditambah lagi, peran polusi tanah, air, dan udara yang memperberat keseimbangan lingkungan. Kondisi ini sangat erat dengan kesehatan manusia. Selain itu, kondisi ini juga berhubungan dengan degradasi ekosistem dimana terjadi perubahan pada dua penyangga utama ekosistem (hutan dan pertanian).
Ketidakseimbangan keberagaman biologis (biodiversity loss) memfasilitasi hubungan manusia-alam pada kondisi rentan terhadap kemunculan dan penularan penyakit zoonosis (penyakit yang diperantarai oleh binatang).
Di sisi lain, kemunculan COVID-19 berbarengan saat ekonomi global yang berbasis pada perdagangan domestik dan internasional yang mempercepat degradasi habitat di pelbagai negara, khususnya di negara berkembang.
Selain itu, transportasi pada perkembangan ekonomi global juga menjadi portal bagi pesatnya penularan COVID-19 secara global.
One health sebagai urgensi dan strategi pendekatan penanganan pandemi dan pasca-pandemi
One Health, menurut Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), didefinisikan sebagai suatu strategi yang menggunakan pendekatan secara terintegrasi pada upaya menjaga keseimbangan dan optimalisasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Strategi ini tentunya sangat diperlukan untuk mencegah, memprediksi, mendeteksi, dan menangani tantangan kesehatan global seperti halnya pandemi COVID-19. Pendekatan One Health menggerakkan seluruh lini/sektor, disiplin kepakaran, dan komunitas pada pelbagai tingkat sosial untuk bergabung dan bekerja sama.
Dalam upaya realisasi One Health menjadi suatu gerakan kolektif multidisiplin, WHO membentuk One Health Initiative dengan merangkul beberapa institusi internasional terkait lainnya, yakni the Food and Agriculture Organization (FAO), the United Nations Environment Programme (UNEP), dan the World Organization for Animal Health (WOAH), yang kesemuanya disebut juga sebagai One Health Quadripartite.
Beberapa isu terkait One Health mencakup penyakit emerging (penyakit yang baru muncul), penyakit re-emerging (penyakit yang sudah ada sejak lama dan sudah tereradikasi namun muncul kembali), endemi penyakit zoonosis, resistensi antibiotik, keamanan dan ketahanan pangan, kontaminasi lingkungan, perubahan iklim, dan ancaman kesehatan lainnya.
Sebagai contoh, kuman yang kebal terhadap antibiotik dapat menyebar secara cepat melalui komunitas, cadangan makanan, fasilitas umum, dan lingkungan (tanah, air) sehingga menyebabkan sulitnya penanganan kasus infeksi pada manusia dan hewan.
Mengapa konsep One Health ini penting? Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, akan terjadi ekspansi area geografis yang baru sehingga mengakibatkan banyak manusia yang hidup/tinggal berhubungan erat dengan lingkungan dan hewan 'liar'.
BACA JUGA:Telkomsel Hadirkan Beragam Layanan di COOLtura Cirebon 2025
Hewan tentunya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pada konteks tertentu, kontak populasi manusia dan hewan/lingkungan liar yang erat memungkinkan munculnya penyakit, yang juga dikenal sebagai penyakit zoonosis (penyakit yang dibawa oleh atau terkait dengan hewan).
Selain itu, bumi telah mengalami perubahan iklim dan penggunaan tanah, seperti penggundulan hutan dan praktik pertanian intensif. Disrupsi lingkungan dan habitat ini tentunya dapat memungkinkan munculnya penyakit.
Pergerakan manusia, hewan, dan produk hewan telah meningkat secara signifikan seiring dengan kemajuan transportasi dan perdagangan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Hal ini dapat menyebabkan cepatnya penyebaran penyakit secara global.
Konsep One Health ini diwujudkan dengan berasas pada komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Saat pandemi COVID-19, pendekatan ini mengurangi kejadian kasus baru dan penyebaran infeksi dengan supervisi dari berbagai kepakaran multidisiplin, misal pakar hewan meninjau kondisi kesehatan dan keterkaitan hewan, pakar lingkungan menilai keterkaitan aspek lingkungan dan perubahan iklim, dan dokter beserta epidemiologi dan pakar kesehatan masyarakat menangani dampak pandemi terhadap manusia.
Tentunya, terdapat aspek penting lain yang dapat menjaga kontinuitas One Health ini, yakni penentuan kebijakan, penegakan hukum/regulasi, agrikultur, komunitas, dan lain-lain.
One Health sebagai strategi gotong royong ini seharusnya tidaklah merupakan strategi yang kaku dan rumit bagi negara kita yang memiliki budaya gotong royong. Konsep One Health ini tentunya dapat terlaksana di berbagai tingkat, dari nasional hingga desa.
Forum dan konsorsium yang tengah dan telah ada di masyarakat baik di tingkat nasional maupun di tingkat desa dapat diformulasikan lebih lanjut sebagai realisasi program keberlanjutan di bidang kesehatan bagi forum/konsorsium tersebut.
Hal ini tentunya untuk mewujudkan resiliensi masyarakat Indonesia yang tumbuh dari desa terhadap ancaman kesehatan global.
dr. Ahmad Fariz Malvi Zamzam Zein, SpPD, FINASIM, FACP
Akademisi dan Praktisi Kesehatan
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: reportase